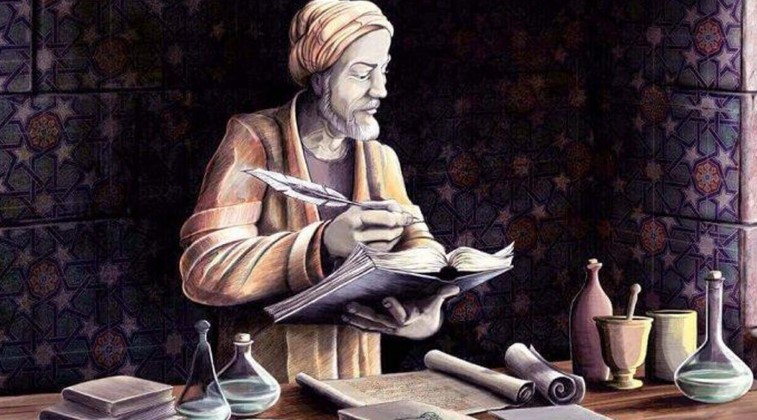Dalam filsafat hukum Islam, ada seorang ulama yang sejak lama saya kagumi pemikiran dan produk keilmuan yang dihasilkannya. Bahkan sejak semester 5 (awal saya mengenal ilmu beliau), saya sangat tertarik dengan corak pemikirannya. Ya, Imam Syatibi, pencetus sekaligus penggagas teori Maqashid Syariah, teori yang masih sangat relevan dengan era modernitas saat ini.
Imam Syatibi sendiri memiliki nama lengkap Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati. Lahir di Granada (yang saat itu sangat dipengaruhi oleh peradaban Bani Umayah di Andalusia) pada tahun 730 Hijriyah, atau kalau dimasehikan 1328 Masehi. Syatibi sendiri adalah nama yang dinisbatkan pada suatu nama daerah bernama Syatibah, tempat ayah Imam Syatibhi dilahirkan.

Dalam bidang Ushul Fiqih, Imam Syathibi berguru kepada kepada Syekh Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Syarif al-Tilmisani pada 771 H. Imam Syathibi ketika berguru pada Syekh Abu Abdillah memiliki teman yang juga merupakan ilmuan muslim, yakni Ibnu Khaldun. Selanjutnya, beliau melanjutkan pengembaraan keilmuannya dalam Ushul Fiqih kepada Khatib Ibn Marzuq.
Ulama sepakat bahwa Imam Syatibhi merupakan tokoh dalam teori Maqashid Syariah. Alasannya adalah karena beliau yang secara sangat sistematis berhasil menyusun teori atau ilmu maqashid. Ilmu maqashid yang disusun oleh Imam Syathibi lebih sistematis dan lebih lengkap dari pada teori-teori yang ada sebelumnya.
Tidak hanya Ushul Fiqih, pengembaraan keilmuan Imam Syatibhi juga meluas terhadap ilmu-ilmu lain, seperti ilmu-ilmu gramatika bahasa Arab, Tafsir, Teologi Raional, hingga ilmu Filsafat dan Kalam. Keilmuan-keilmuan inilah yang bisa dipastikan membentuk kerangka berpikir Imam Syatibhi, yakni Maqashid Syariah.
Pengembaraan keilmuannya itu pun juga dimentori oleh ulama-ulama besar dan pakar di bidangnya masing-masing. Misal, dalam ilmu Gramatika, Imam Syatibi belajar kepad Abu Abdillah al-Birri, ulama besar Bahasa Arab, setelah itu (setelah Imam al-Birri wafat), Imam Syatibi melanjutkan bergurunya kepada mufassir terkenal, Imam al-Syarif al-Sabti.
Dalam ilmu Tafsir, ia belajar kepada ahli tafsir Syekh al-Balansani. Dalam bidang Hadis berguru kepada Syekh al-Qasim ibn al-Bina dan Syekh Syamsuddin. Dalam ilmu Filsafat, ia belajar kepada Abu Ali Manshur. Dari sini juga, Imam Syatibhi mengenal pemikiran Mu’tazilah dan pemikiran rasional lainnya.
Karyanya sendiri pun banyak. Ushul Nahwu, Fatawa al-Syatibi, Ifadat wal-Insyadat, dan yang paling monumental adalah al-Muwafaqat, kitab yang disusun oleh al-Syatibi persis 50 tahun sebelum runtuhnya kota Granada, kota muslim terakhir di Andalusia. Kitab ini yang berisi teori-teori yang membahas tentang mashlahah, hingga tentang signifikansi teori Maqashid Syariah.
Maqashid Syariah
Kehidupan akan selalu mengalami perubahan (dinamis), ia tidak akan bersifat statis. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, apalagi setiap abad, manusia dan peradabannya lambat laun akan berubah. Kebutuhan pun akan terus mengalami eskalasi. Maknanya, kehidupan era Nabi dengan kehidupan saat ini adalah dua realitas yang tidak sama di banyak sisi.
Dengan adanya perbedaan tersebut, maka penyesuaian demi penyesuaian harus berjalan agar menjadi seimbang. Laju perubahan yang ada hendaknya diilhami sebagai tuntutan agar kita lebih memiliki kreativitas untuk perubahan tersebut. Salah satu hal yang mengalami perubahan antara lain adalah hukum, khususnya hukum Islam. Agar tidak terkesan statis, hukum fikih (hukum Islam) tentu terus mengalami elastisitas untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan.
Yusuf Qardlawi menyebut bahwa para intelektual muslim butuh melakukan ijtihad agar nalar fikih tidak mandek dan rigid. Salah satu indikator kemandekan tersebut adalah ketika hukum fikih hanya membahas poin-poin tentang ibadah dan tidak menyentuk aspek lain, semisal muamalah. Hal seperti itu—menurut Yusuf Qardlawi—adalah bentuk cara pandang fikih yang mandul terhadap persoalan lain, semisal politik, ekonomi, dan lainnya.
Alih-alih mengatakan pintu ijtihad tertutup, Abdurrahman Kasdi dalam tulisannya bertajuk Reinterpretasi Teori Maqashid Syariah dan Implementasinya dalam Kehidupan Kontmporer justru mengatakan sebaliknya. Sampai saat ini—menurut Kasdi—pintu ijtihad itu masih terbuka, hukum Islam (Fikih) harus benar-benar elastis dengan dinamika zaman yang masih belum berhenti.
Maqashid Syariah sendiri ada karena kegelisahan sejumlah intelektual muslim atas dinamika zaman tersebut. Salah satunya Imam Syatibi sendiri, sehingga beliau membuat rancangan yang sistematis ihwal Maqashid Syariah sebagai acuan dalam melakukan penggalian hukum yang lebih responsif dan solutif. Maqashid dipakai sebagai sebuah cara untuk beristinbath dan penting untuk dilirim oleh ulama Ushul di abad modern saat ini.
Maqashid Syariah sering diartikan sebagai tujuan syara’ atau syariat. Dalam kitabnya, al-Muwafaqat, Imam Syatibi berpendapat bahwa syariat itu ditetapkan atas dasar dan sebagai kemashlahatan manusia selama hidup di dunia hingga di akhirat kelak. Hukum berlaku tidak lain adalah untuk kemashlahatan manusia, begitu kira-kira.
Sehingga, adanya Maqashid Syariah dianggap perlu sebagai acuan kemashlahatan tadi, sembari menerapkan ajaran syariat yang sesuai dengan kemashlahatan manusia. Sehingga mashlahah (maslahah mursalah) menjadi hal utama dalam term ini.
Maqashid Syariah terbagi menjadi 5 aspek. Lima aspek itu antara lain hifdz nafs (msnjaga jiwa), hifdz din (menjaga agama), hifdz aql (menjaga akal), hifdz nasl (menjaga kehormatan), hifdz mal (hifdz harta). Hukum syariat yang ditetapkan harus selalu berorientasi atau bergenealogi pada lima aspek itu untuk menjamin mashlahah yang dimaksud.
Di sinilah–sebagaimana dalam Filsafat Hukum Islam–Imam Syatibi kemudian membaginya menjadi tiga tingkatan, yakni: dharuriyat (primer), hajjiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Sedangkan, 5 aspek yang telah saya sebutkan di depan termasuk pada kategori dharuriyat.
Tingkatan dharuriyat ini adalah tingkatan yang apabila tidak terpenuhi maka kemashlahatan akan terancam. Imbasnya, akan menyebabkan kerusakan dan bahaya lain. Maknanya, semuanya berorientasi pada 5 aspek. Jika tidak, maka akan terjadi ketidak normalan di dalamnya.
Selanjutnya adalah tingkatan hajjiyat (primer). Tingkatan ini jika tidak bisa diwujudkan tidak akan mengancam keselamatan, sebagaimana dalam tingkatan dharuriyat. Namun, hanya akan mengalami kesulitan. Dalam Islam, khususnya dalam pembahasan mengenai ibadah, kita mengenal rukhshah (dispensasi hukum). Ia ada sebagai contoh nyata dari tingkatan ini. Jika rukhshah (misal rukhshah-nya orang hamil tidak berpuasa) tidak ada, maka akan terasa sulit. Sedangkan, kesulitan bukan termasuk dari agama.
Dan yang terakhir adalah tahsiniyat (tersier). Tingkatan ini tidak sampai seperti tingkatan sebelumnya, namun juga dianggap perlu. Misal dalam ibadah, Islam menganjurkan untuk ibadah sunah, bersih-bersih badan, dan berhias sebelum pergi ke mesjid, dan lainnya.
Maka dengan teori-teori Maqashid Syariah ini, selayaknya bisa memberikan terobosan dalam pembaharuan hukum Islam. Tidak hanya itu, dengan teori ini, permasalahan ihwal sosial kemanusiaan bisa teratasi dengan menjadikan maqashid sebagai pijakan dan orientasi dari segala ketetapan hukum yang ada. Sehingga, kemashlahatan dari segi apa pun (jiwa, harta, agama, keturunan, dan kehormatan) bisa terjamin. Wallahu a’lam…