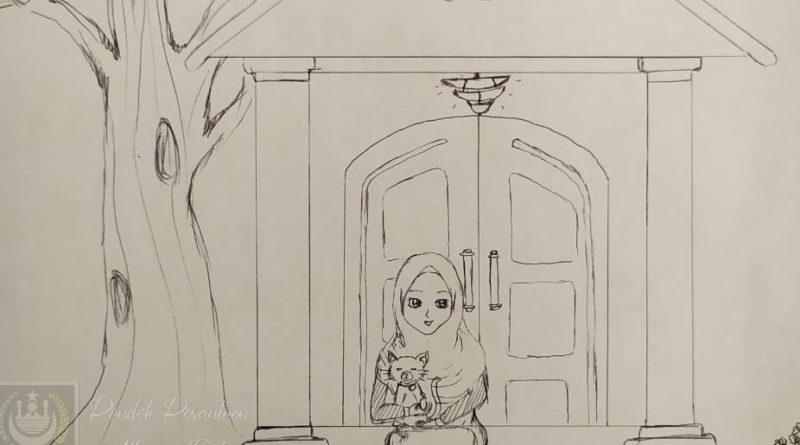Setiap pertengahan Muharam aku selalu mendapat permen, tasbih, dan surat. Namun tahun ini tidak. Aku hanya mendapat telepon dari rumah, bahwa seseorang telah melamarku dan kini mereka menunggu jawaban. Aku tutup telepon dan berlari keluar, masuk ke kamar kecil, dan menangis lalu tertawa.
***
Setiap santriwati mendapat surat dan permen, tak terkecuali ustazah yang berjaga di koperasi, yang setiap hari mendapat titipan surat. Namun, setelah pintu gerbang santriwati selesai dibangun, tidak ada lagi surat dan permen.

Saat itu Jumat pagi, semua santriwati kerja bakti. Aku dan dua temanku dapat bagian membersihkan gudang. Satu temanku pergi mengambil sapu dan satunya membantuku menurunkan karung di atas tumpukan barang bekas. Tiba-tiba karung itu jatuh dan berhenti di depanku, lalu sesuatu mendarat di depan kakiku. Sebuah surat yang di sisi kanan bawah tertera tulisan: Teruntuk Fatimah.
Semenjak itu aku selalu membaca kalimat awalnya. Dan membayangkan seorang pangeran yang jauh di negeri sana mengirimkan surat padaku yang terkurung di kastil. Aku selalu saja membayangkan akan hal itu.
Esoknya, ketika aku kembali untuk menaruh sapu yang rusak, karung itu sudah tidak ada, dan kurasa ustazah sudah membuangnya. Aku berlari ke belakang asrama. Di sana, pada gerobak pengangkut sampah karung itu tertumpuk bersamaan dengan plastik dan pembalut. Aku mendengus dan menyumpahi ustazah.
Belum tuntas rasa kesalku pada ustazah, aku tidak masuk kelas belajar malam. Aku membawa surat yang kemarin ke atas loteng, tempat biasa teman-teman menjemur pakaian. Di sana aku biasa menyendiri sambil melihat bintang yang berkedip. Lalu aku mulai membaca surat itu dua-tiga kali sampai bel tengah malam berbunyi. Semua lampu dimatikan dan aku segera mengatupkan mata sembari melipat surat dan menyelipkannya ke dalam dada.
Sesuatu di dalam dadaku bergolak kencang dan ingin keluar. Setiap kali membaca surat itu, aku merasakan hal yang sama. Aneh. Sesuatu yang tidak kumengerti namun begitu dekat.
Teman kamarku pernah bertanya ketika aku sedang asyik membaca dan mengejanya pelan, “Kenapa akhir-akhir ini kau terlihat aneh?”
Mendengar pertanyaannya membuat isi perutku meledak dan aku tertawa terkekeh.
“Aku hanya memikirkan pangeran di negeri sana, mengirim surat pada tuan putri.” Aku memberi jeda lalu melanjutkan, “Lalu aku membayangkan bahwa tuan putri itu adalah aku.”
Teman kamarku balik tertawa.
***
Pagi-pagi sekali setelah kemarin menunggu surat darinya tidak datang. Orang tua dan adikku datang ke pesantren.
“Besok dia akan kemari menjemputmu,” kata Asmad, ayahku
“Kau pasti bahagia bersamanya, Nak,”.tambahnya. Pembicaraan berhenti ketika bel berbunyi. Aku keluar ruang tamu dan masuk kelas.
Di kelas semua temanku berebut tanya. Mereka ingin tahu keputusanku. Aku tidak menjawab pertanyaan mereka yang semuanya sama. Ustazah datang dan mesem-mesem padaku. Ia menyuruhku keluar agar menemui tamuku di ruang tamu. Teman-teman kelas menyorak, “Tuan putri, tuan putri, jangan lupa kembali.”
***
Setelah beberapa hari berpikir, aku memutuskan untuk menulis surat balasan untuk si pangeran. Pada akhir surat aku bubuhkan tanda tangan serta namaku di bawahnya. Lalu kulipat dan kutulis nama si pangeran di sisi atas.
Surat itu kutitipkan pada khodim di dapur. Ia sering dititipi surat oleh teman kamarku. Sehingga ia paham betul maksudku berdiri di pintu dapur sambil berdecak.
“Tunggu barang seminggu kekasihmu akan mengirim balasan,” katanya sembari memasukkan surat itu ke dalam saku.
Benar. Tidak lama dari itu setelah sepuluh hari menunggu surat balasan kuterima. Bukan hanya surat yang berisi puisi melainkan satu potong cokelat. Tiba-tiba dadaku bergolak sangat cepat, jemari gemetar saat membuka kulit coklat. Beginikah rasanya? Kami saling mengirim surat, dan dia membalas dengan cokelat pula gambar hati. Begitu seterusnya sampai satu hari di bulan Muharam, aku menunggu di balik jendela menantikan surat darinya.
Namun sesuatu terjadi setelah aku mendapat surat dan coklat yang ke empat kalinya. Semua santri disuruh keluar dan berbaris di depan asrama. Kami tidak boleh memakai sendal. Di sana kami benar-benar dijemur oleh terik. Sementara beberapa ustazah hilir mudik masuk kamar. Membongkar rak kitab dan menggeladah lemari. Kamar menjadi berantakan tak seperti kamar perempuan.
Sesaat ustazah keluar dari masing-masing kamar membawa selembar kertas. Lalu ustazah di depan kami mulai berkata dengan lantang.
“Mulai saat ini tidak ada lagi santriwati yang mengirim surat pada santri putra. Apa pun statusnya, kakak, adik, sepupu. Ketetapan ini berlaku sampai kalian lulus…,” kami diam. “Mengerti?” kami mengangguk tapi aku diam-diam aku menggeleng.
Asrama putri benar-benar menjadi kastil. Aku selalu saja menunggu di balik jendela kamar, dan membayangkan seekor burung mengantarkan surat padaku. Lalu ia akan pergi membawa surat balasanku. Tapi nyatanya tidak ada. Tidak ada surat, tidak ada coklat. Bahkan di bulan Muharam.
***
“Besok ayah dan calonmu datang menjemput. Pastikan pakaianmu sudah berada di tas,” kata ayah yang pulang bersama adikku. Tak ada yang perlu kukhawatirkan semuanya akan baik-baik saja. Dan aku masih percaya pangeran akan datang eok pagi sebelum ayah menjemput. Lalu mereka akan terkejut tidak menemukanku di kamar.
Apakah itu konyol? Kurasa tidak, karena seseoang berhak berkhayal. Apalagi perempuan sepertiku, mengkhayal menyelamatkanku dari keterpurukan. Namun kenyataan tidak bisa ditolak, semua terjadi dan aku masih menunggu di balik jendela kamar berharap pangeran datang menjemput.
Malam larut begitu cepat. Aku sudah lupa bagaimana bulan tengkurap di sana. Fajar datang, dan aku masih berjaga di balik jendela kamar. Aku tidak perlu ke mana-mana bahkan pada pria yang tidak kukenal dan kini melamarku secepat itu. Aku tak berhasrat padanya. Aku bahkan tak mengenal tulisannya. Dia pun tak pernah mengirim coklat saat Asyura.
Yang mengejutkanku pagi ini. Seseorang, lelaki tampan yang tidak kukenal menungguku di ruang tamu. Dan saat bertemu, ia berdiri dan menjulurkan sepotong coklat padaku.
***
“Aku Ramadhan, senang bertemu denganmu, Fatimah.” Aku diam. Sesaat mataku menyapu matanya.
“Kenapa kau bisa tahu namaku?”
Lelaki itu tersenyum dan tampak lesung pipinya.
“Maaf, sepertinya aku salah orang. Permisi,” lelaki itu beranjak pergi namun berhenti di depan pintu keluar.
“Apa kau lelaki itu?”
Lelaki itu menoleh. Tersenyum lagi.
“Kalau kau hanya mengharap cokelatku, aku sudah berikan yang kau mau. Tapi sepertinya aku salah orang. Permisi.”
Pangeran itu benar datang ke kastil. Ia tidak kukenal namun ia mengenalku lebih dari diriku sendiri. Sebelum ia benar-benar pergi, aku mengejarnya, melompati pintu, tidak tahu, kakiku begitu ringan sampai aku bisa meraih pundaknya. Ia menoleh dan aku kembali menyapu matanya yang tenang. Ia tersenyum, dan aku pun tersenyum. Beberapa santri melihat kami. Aku tak peduli. Lalu terdengar suara yang begitu kukenal.
“Sebentar lagi kalian akan sah menjadi suami-istri.”