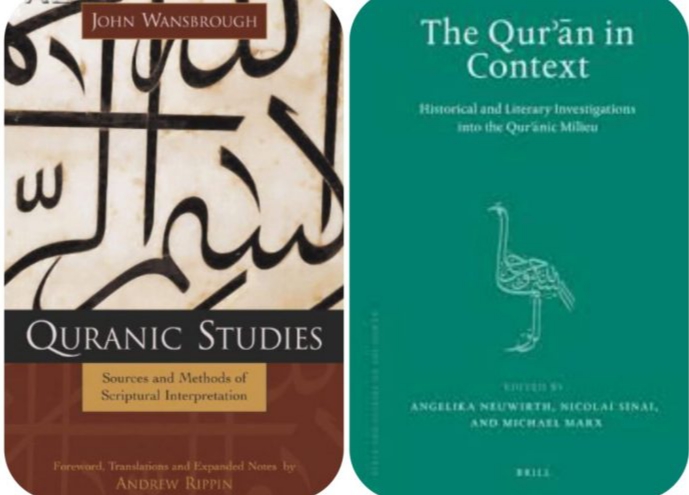Setiap kali saya membaca ulang Al-Qur’an, saya merasa seperti memasuki ruang spiritual yang dalam dan tidak terbatas. Di luar tradisi Islam, saya menyadari bahwa kitab suci ini tidak hanya digunakan untuk ibadah, tetapi juga digunakan untuk penelitian ilmiah, khususnya dari akademisi Barat yang disebut orientalis.
Di sinilah saya mulai merenungkan satu hal yang sangat penting: mengapa sikap mereka terhadap Al-Qur’an begitu paradoks, antara kekaguman yang mendalam dan kecurigaan yang tajam?

Sebagai santri yang juga tertarik pada dunia akademik, saya merasa perlu untuk menyelidiki lebih jauh cara orientalis memahami Al-Qur’an. Di antara karya mereka, saya menemukan pujian yang tulus terhadap bahasa dan struktur Al-Qur’an yang indah.
Misalnya, terjemahan Al-Qur’an oleh Arthur J. Arberry yang mempertahankan ritme dan keindahan bahasa. Ia menganggap Al-Qur’an sebagai karya sastra Arab terbaik. Sebagai Muslim, saya pasti bangga. Al-Qur’an tetap menarik bahkan bagi mereka yang tidak menganut iman.
Namun, di balik pujian, ada bias yang membuat saya bertanya-tanya: apakah mereka benar-benar ingin memahami atau sekadar membongkar? Banyak orientalis klasik seperti William Muir atau Theodor Nöldeke berpendapat bahwa Al-Qur’an hanyalah tulisan Nabi Muhammad yang memiliki sumber dari Yahudi dan Kristen. Mereka mengabaikan aspek spiritual dan melihat wahyu sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Dengan perspektif ini, saya menyadari bahwa ada alasan di balik apa yang dianggap “ilmiah”.
Saya mulai menyadari bahwa studi orientalis tentang Al-Qur’an berasal dari dua sisi: puja dan prasangka. Pujian mereka memberikan pengakuan, tetapi kebencian mereka menghancurkan otentisitas. Sayangnya, prasangka sering kali berkuasa dalam sejarah. Sebagian orientalis menganggap mereka memiliki hak penuh untuk menilai Al-Qur’an, bahkan hingga hari ini.
Meskipun demikian, saya tidak dapat menolak sepenuhnya penelitian Barat tentang Islam. Selama kita memiliki kerangka berpikir kritis, kita dapat banyak belajar dari metode mereka.