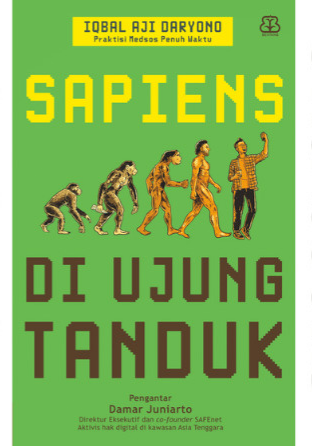Sadar atau tidak, kita telah hanyut di dunia kedua—jika memang istilah ini presisi dan layak. Dunia dengan bungkus maya dan akhirnya disuguhkan di hadapan kita. Implikasinya, tidak ada sarapan nasi yang disusul puding sebagai penawar amis. Semua sarapan pagi kita berganti dengan membuka gawai dan masyuk dalam-dalam. Dari pagi yang satu ke pagi selanjutnya terus seperti itu, seolah menjadi siklus mayoritas umat manusia. Hanya di abad ini, seseorang menafikan estetika bunyi burung atau matahari yang meninggi.
Seandainya disuruh menulis cerita, beberapa orang kemungkinan menolak memulainya dengan ungkapan klise “di pagi yang buta, matahari membuka mata”. Alih-alih begitu, kemungkinan besar memilih dengan pembuka “sebuah notifikasi tiba-tiba menyembul di pagi hari”. Tenang saja, ini hanya kelakar dan sebuah usaha dari saya untuk mengungkapkan beberapa pergeseran di pagi hari. Memang, masih ada bapak yang menyeruput kopi, tetapi di tangan kanannya juga terdapat telepon pintar.

Dunia berubah dan siapapun dipaksa untuk hanyut di dalam perubahan tersebut. Dinamika dunia digital menunjukkan taringnya dan mengkonstruk siapa saja yang terjun. Iqbal mengungkapkan dengan gayanya yang khas bahwa ia dipaksa berbicara. Maksudnya, di dunia yang serba digital, medsos lebih tepatnya, semua orang mesti berbicara. Apalagi, orang yang dipandang punya suatu kompetensi dalam satu ranah keilmuan. Itulah yang penulis rasakan ketika dituntut untuk berbicara oleh salah seorang temannya.
Sebelum era pradigital, manusia—atau kita lebih tepatnya—hanya seseorang yang menikmati berita. Pergeseran kemudian ditemukan tatkala memasuki dunia yang diklaim menawarkan kepraktisan. Akhirnya, siapapun dipaksa untuk berbicara dan mencoba menawarkan gagasannya masing-masing. Barangkali ini yang disebut sebagai demokratisasi wacana oleh Iqbal sebagai penulis. Sungguh menarik, jika kita melihat bagaimana wacana tidak hanya dimonopoli oleh sekelompok orang tertentu.
Dahulu, yang mewartakan wacana hanya orang yang sudah melewati proses seleksi yang ketat. Ada kompetensi-kompetensi yang harus dipenuhi jika memang hendak menawarkan wacana. Kasarnya, ada serangkaian usaha eklektik dari pihak media(waktu itu masih cetak) untuk menampilkan gagasan yang ditawarkan seseorang. Berbanding terbalik dengan era digital yang kesemuanya tidak pernah melewati fase seleksi, tidak ada usaha eklektik. Apalagi jika disangkut pautkan dengan media sosial yang setiap orangnya memang berhak coret-coret di dinding masing-masing.
Dengan sebab yang tidak dapat ditolak ini, bah informasi menggenangi kepala kita. Kita sedang diterjang banjir bandang informasi, Iqbal menyebut demikian. Dengan kemampuan filter informasi yang masih sangat minim, berita bohong bukan lagi hal yang naif dan langka. Artinya, kridibelitas sebuah informasi yang sejujurnya bisa dipertanyakan pada era ini mulai tidak ada yang memerhatikan. Tidak peduli apakah itu berita bohong, provokatif, dan lain semacam. Selama hal tersebut berada di layar gawai kita, maka ditelan mentah-mentah oleh sebagian besar umat manusia.
Di tengah limbah informasi tersebut, penulis coba menyentil intelektual tanah air yang masih berada di menara gading. Bagi Iqbal, kuran afdal jika intelektual yang sudah matang dan kompeten di satu bidang keilmuan hanya memintarkan orang-orang pintar. Maksudnya, yang hanya sudi menulis di jurnal ilmiah dan cuma diakses oleh orang yang sederajat denga mereka. Padahal, masyarakat awam secara faktual juga butuh dicerahkan. Masyarakat yang dipandang sebelah mata ini juga butuh membaca hasil penelitian mereka dengan penyampaian yang sederhana, tanpa bahasa yang mengernyitkan kening.
Selama ini pamor intelektual tanah air sering berkisar pada publikasi di jurnal ilmiah. Beberapa orang yang mengaku intelektual justru enggan menyentuh medium-medium potensial yang bisa diakses banyak orang. Padahal di medium inilah kementakan orang bawah membaca dengan cermat dan khidmat gagasan mereka. Berbeda dengan jurnal yang hanya dibaca oleh segelintir orang, mentok-menotok 10 orang. Perihal angkat 10 orang ini merupakan hasil pengamatan dari Asit Biswas dan Julian Kirchherr. Nama pertama merupakan professor dari National University of Singapore, sedang yang peneliti terakhir di University of Oxford.
Barangkali atas dasar inilah, penulis terpantik dan tebersit di dalam hatinya untuk melihat potensi dari media sosial. Media sosial memang diklaim mampu menggunting jarak antara seorang profesor dengan seorang pengangguran. Di media sosial juga, gagasan-gagasan para raksasa intelektual harusnya bisa dinikmati oleh orang yang sepantasnya mendapat itu. Bukan ujug-ujug dan hanya atas nama gengsi intelektual sehingga tidak mau mengisi ruang yang terbuka itu. Dalam bahasa penulis, ikut nyebur tetapi tidak harus ikut arus.
Di dunia yang serba terhubung ini dengan koneksi yang tidak putus hanya karena jarak, juga terdapat semacam pergeseran orientasi dari lelaku yang pada dasarnya hanya aktivitas biasa. Iqbal mencoba menguraikan bagaimana hal tersebut terjadi lagi-lagi demi hasrat yang pada titik hakikinya semu. Ambil contoh membaca buku yang pada zaman pradigital merupakan aktivitas untuk memeras otak dan mengendorkan saraf-saraf yang tegang. Jauh panggang dari api, jika kita melihat hal tersebut hari ini, detik ini. Membaca buku tidak hanya sebuah aktivitas biasa yang dilakukan oleh sebagian besar umat manusia. Orientasinya berubah menjadi ajang pertunjukan yang berujung pada hasrat untuk dipuji banyak orang(hlm. 76).
Secara faktual memang benar, jika dikatakan ada pembengkokan orientasi ketika media sosial ini menguasai. Membaca buku tidak hanya sekadar membaca buku. Ada sesuatu di balik itu semua, kendati sesuatu tersebut hanyalah semu belaka. Perlu dicatat, hal ini tidak lantas menjadikan membaca buku sebagai sesuatu yang buruk, sama sekali tidak. Namun, penulis mencoba untuk menilik bagaimana pergeseran orientasi yang terjadi ketika semua harus terekspos ke media sosial. Di saat yang bersamaan ia mencoba mempertanyakan bagaimana seandainya tidak ada media sosial. Apakah hasrat membaca akan meletup-letup tanpa ada medium untuk memamerkan setelahnya? Ini pertanyaan serius dan menjengkelkan. Menjengkelkannya musbab Iqbal sendiri sudah tahu(atau mengira-ngira?) jawabannya.
Dan implikasi paling besar dari dunia digital tidak lain adalah hilangnya kecerdasan dan potensi alamiah dalam diri manusia. Ketika teknologi berkembang kian lesatnya, kemampuan alami kita pelan-pelan raib. Barangkali ingatan tentang arah jalan dan kelokan serta gang-gang sempit sudah mulai habis. Walaupun tidak nyaris habis terkikis, tetapi nyaris sepenuhnya dipasrahkan pada fitur Google Maps. Tidak ada yang salah, tetapi potensi dan bakat alami mengingat nama jalan dan bentuk lika-likunya mulai tergantikan. Tidakkah kita khawatir bahwa suatu saat justru otak dan kemampuan kita tidak lagi dibutuhkan?
Terakhir, pada era realitas yang kedua ini, siapapun berhak membangun panggung sendiri-sendiri. Semua bebas bereskpresi, yang sekali lagi saya katakan, dalam Iqbal disebut demokratisasi wacana. Setiap yang terlahir ke dunia berhak membangun panggungnya masing-masing. Tergantung sejauh mana kreativitas dan kemauan untuk membangun panggung tersebut. Sejujurnya, klimaks dari ini semua adalah satu: kita tidak boleh mendudukkan dunia maya sebagai realitas kedua. Kita harus meningkap itu dan menjadikannya sebagai realitas yang pertama(utama?). Sementara, buku ini mencoba mengajari bagaimana menyingkap yang tak terkatakan di dunia yang selama ini diletakkan sebagai realitas kedua.
Data Buku
Judul: Sapiens di Ujung Tanduk
Penulis: Iqbal Aji Daryono
Penerbit: Bentang Pustaka
Tahun: 2022
ISBN: 978-6-2-291-897-4