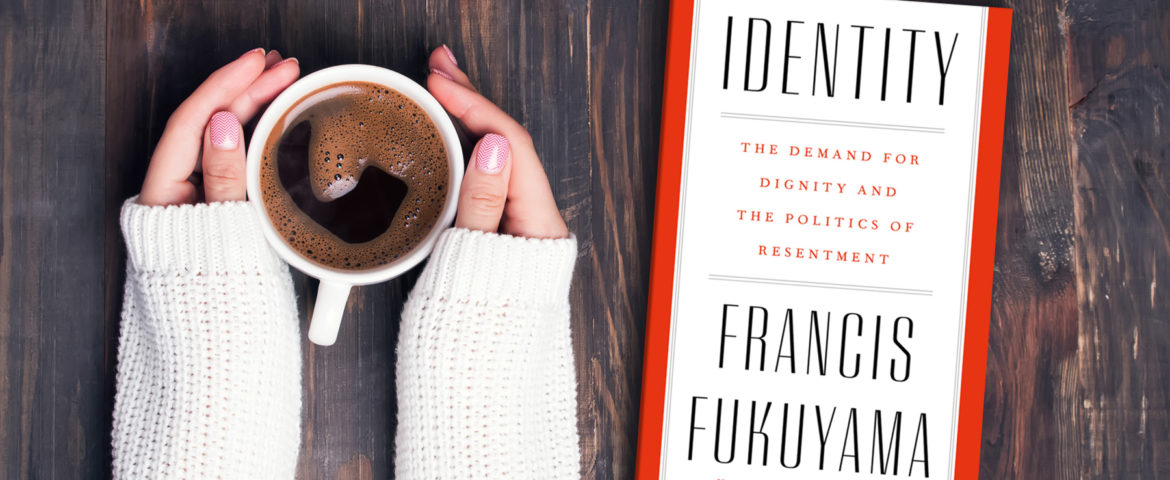Jangan teralu nelangsa jika di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir politik identitas menguat, dilengkapi dengan maraknya politik kebencian. Gejala itu bukan cuma terjadi di Indonesia. Gejala serupa justru lebih dulu terjadi di berbagai negara, bahkan di negara-negara maju dengan tradisi demokrasi yang kuat, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Memang terasa dan terlihat sebagai ancaman yang mengerikan bagi keberlangsungan demokrasi global. Namun, Francis Fukuyama yakin pada akhirnya gejala tersebut akan menemukan titik keseimbangan baru dan akan memperbaiki sistem demokrasi yang saat ini “dibajak” politikus-politikus populis.

Francis Fukuyama, yang sohor melalui karya fenomenal The End of History and the Last Man (1992), mencoba menelusur akar-akar politik identitas dan politik kebencian hingga ke masa-masa yang jauh di belakang. Buku ini, Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, terbit pertama kali pada 2018, ketika politik identitas, politik populis, dan politik kebencian meraja di Amerika Serikat dan mengantarkan Donald Trump ke Gedung Putih. Dalam edisi Indonesia, Identitas diterbitkan Bentang pada 2020.
Buku setebal 263 halaman ini terdiri atas 14 bab. Pada bagian-bagian awal, Fukuyama menelusur akar-akar politik identitas dan politik kebencian hingga ke masa-masa yang jauh ke belakang sebelum orang mengenal istilah bangsa (nasion) dan negara modern (nasion-state). Fukuyama membongar khazanah para pemikir terdahulu sejak Yunani kuno hingga Revolusi Prancis dan Revolusi Industri.

Dari sana, Fukuyama menyimpulkan bahwa politik identitas, dan kemudian politik kebencian, lahir dari apa yang ia sebut thymos beserta turunannya, isothymia dan megalothymia. Thymos diartikan sebagai bagian dari jiwa yang sangat membutuhkan pengakuan akan martabat sebagai manusia. Sedangkan, turunannya, isothymia merupakan tuntutan untuk dihormati atas dasar kesetaraan dengan orang lain dan megalothymia merupakan keinginan untuk diakui sebagai yang lebih unggul.
Thymos dan isothymia inilah yang sebenarnya mendorong lahirnya negara-bangsa modern yang dikelola dengan sistem demokrasi. Namun, ketika demokrasi tak juga menyuguhkan apa yang dimaui thymos dan isothymia, dunia kemudian bergerak memutar dan mundur. Itulah yang terjadi di berbagai belahan dunia, di Amerika Serikat, Eropa, Benua Afrika, juga Asia —ketika demokrasi tak berjalan dengan semestinya.
Ketika sosialisme-komunisme runtuh, yang tinggal memang demokrasi liberal. Namun, demokrasi liberal juga tak serta merta memenuhi harapan semua orang. Di Amerika Serikat ketimpangan ekonomi terus melebar, masyarakat kian terjepit dengan ancaman gelombang migrasi, dan perlakuan tidak adil masih menjadi pemandangan sehari-hari. Dalam situasi seperti itulah muncul politikus-politikus populis haus kekuasaan, dengan representasi par excellence Donal Trump melalui jargon America First. Maka benih-benih politik identitas dan kebencian tersemai dengan sempurna.
Gejala serupa terjadi di negara-negara Uni Eropa. Politik identitas, dan identitas nasional, kian menyempit dan menajam. Brexit, keluarnya Britania Raya, Inggris, dari Uni Eropa adalah reprentasi “menyempitnya identitas nasional” negara-negara Uni Eropa. Kawasan lain juga dilanda gejala serupa.
Namun, yang mengherankan Fukuyama, bandul politiknya justru bergerak ke kanan, bukan ke kiri sebagaimana mestinya. Pengelompokan politik tidak lagi didasarkan pada kelas, melainkan identitas. Pada masa sebelumnya, jika pelaksanaan demokrasi menghadirkan ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan, kelas-kelas masyarakat yang merasa dirugikan akan memberikan dukungan kepada partai-partai kiri, sebutlah partai sosialis-komunis. Yang terjadi sekarang, di era politik populis, justru sebaliknya. Mereka bergabung dan mendukung partai-partai kanan, sebutlah partai ultranasional atau nasionalis sempit atau partai agama. Artinya, pengelompokan tidak didasarkan pada kepentingan kelas, melainkan agama dan nasionalitas.
Inilah, juga, yang dibaca oleh Fukuyama terhadap suburnya radikalisme-terorisme di kalangan kaum Muslim di kawasan Eropa dan Asia. Berdasarkan penelitian yang dia kutip, radikalisme dan terorisme muncul di kalangan Muslim generasi kedua yang bermigrasi dari kawasan Timur Tengah dan Asia ke Eropa. Migran generasi kedua ini sedang mengalami krisis identitas. Mereka ogah mengikuti praktik keagamaan orangtua mereka yang cenderung sufis, namun juga merasa tertolak untuk berintegrasi dengan identitas budaya Eropa modern. Situasi ini dibaca oleh para demagog agama radikalis-fundamentalis, yang mendorong mereka untuk melakukan “perang suci” atas nama keunggulan agama.
Megalothymia, atau merasa diri unggul dan orang lain harus mengakuinya, itulah puncak dari politik identitas dalam pengertiannya yang sempit-negatif masa kini. Difasilitasi oleh masifnya jaringan Internet, melalui media sosial (medsos), maka ujaran kebencian (hate speech) menjadi penanda merajanya politik kebencian. Orang ramai berkelompok berdasarkan kesamaan identitas yang dirasa lebih unggul (megalothymi), apakah itu identitas yang dikonstruksi berdasarkan ras, etnis, atau agama, atau lainnya. Melalui hate speech dan hoax, orang ramai digiring untuk membenci, dan kemudian memusuhi, kelompok lain yang harus dianggap lebih rendah.
Di akhir buku, Fukuyama mengakui bahwa kita tak bisa lari untuk menghindari perihal identitas ini. Namun, ia mengingatkan, sesungguhnya identitas itu terbangun melalui proses yang panjang. Identitas bukan sesuatu yang given. Bukan diberikan lewat kelahiran (biologis). Keragaman identitas memang dapat menjadi faktor pendorong pemecah belah, namun sekaligus dapat menjadi pengintegrasi —seperti bhineka tunggal eka masyarakat Nusantara. Jika masyarakat dunia mampu mengelola keragaman (politik) identitas ini, Fukuyama yakin gejala ini dapat memperbaiki sistem demokrasi yang memang masih belum sempurna.