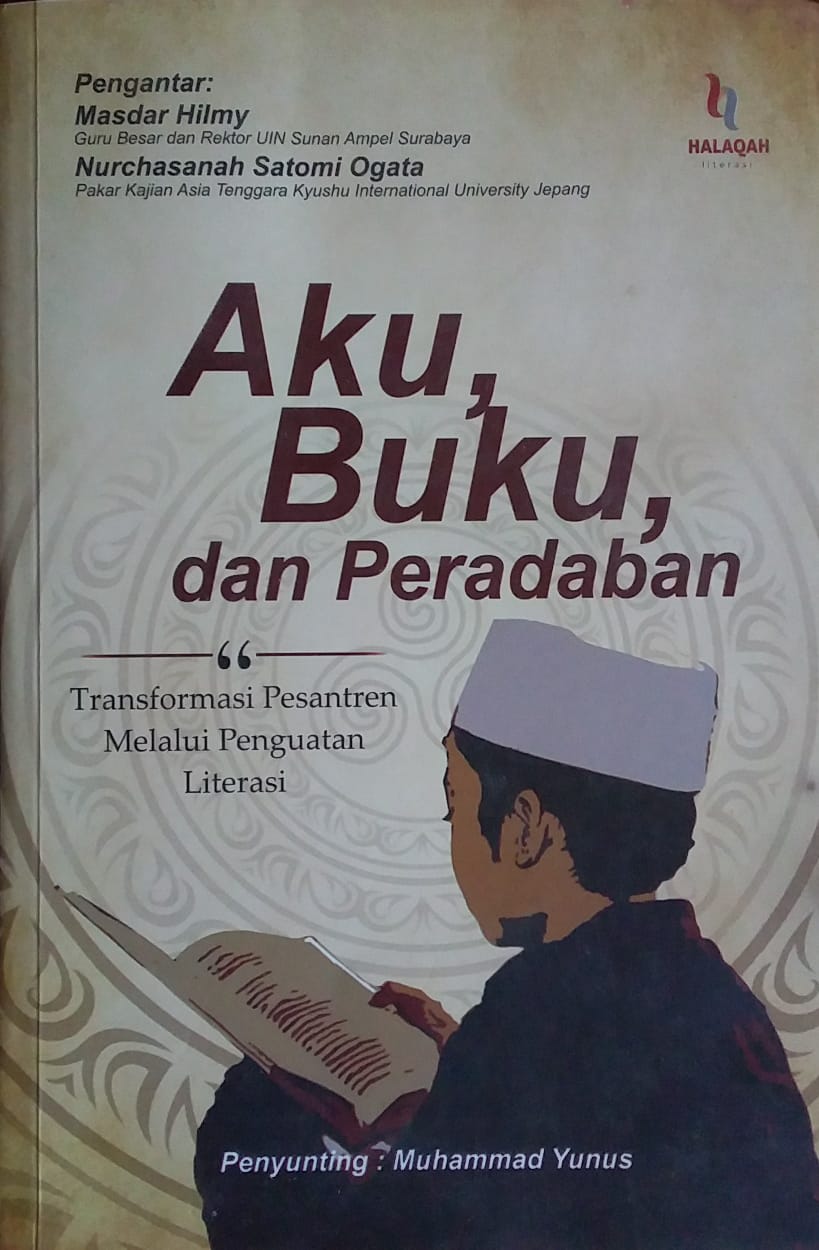Sebuah buku dengan judul Aku, Buku, dan Peradaban: Transformasi Pesantren Melalui Penguatan Literasi, adalah kumpulan teks visual pesantren oleh para santri. Melalui buku ini, kita dibawa pada dunia teks (literasi) yang tumbuh-kembangnya di dunia pesantren. Realitasnya, pesantren adalah lembaga keagamaan, konvensional, dan tradisional yang telah melakukan gerakan literasi secara massif. Literasi yang dimaksud adalah dimensi iqra’ sebagaimana yang dimaksud oleh al-Quran dan Hadits.
Literasi tidak terbatas pada baca tulis semata. Akan tetapi, literasi mempunyai makna menyeluruh yang menurut bahasa Masdar Hilmy (Guru Besar dan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, di dalam pengantar buku ini) bahwa “lebih dari itu, tradisi literasi mensyaratkan adanya keterlibatan nalar yang bertugas mencerna, mengolah, dan mengkritisi berbagai hal yang dianggap cocok atau tidak cocok dengan kebutuhan dasar sebuah peradaban.” (hal. iv).

Masih menurut Masdar Hilmy, setidaknya ada tiga syarat yang harus dimiliki untuk kemampuan literasi. Pertama, kecakapan resepsi, yaitu kemampuan untuk menerima segala sesuatu (yang bermanfaat) yang berasal dari eksternal. Kedua, kemampuan produksi, yaitu kemampuan untuk mencipta segala bentuk narasi ke dalam bentuk deskripsi agar dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Ketiga, kecakapan nalar publik untuk dapat berperan dalam kehidupan bermasyarakat.
Sementara, menurut Nurchasanah Satomi (Pakar Kajian Asia Tenggara Kyushu International University, Jepang, juga dalam pengantar buku ini) mengungkapkan bahwa buku ini banyak menyebut kitab kuning sebagai ciri khas pesantren (hal. ix). Kitab kuning sebagai tradisi pesantren semacam kebutuhan pokok dan wajib adanya. Hal ini menjadi keniscayaan bahwa sebuah pondok pesantren selalu hadir dengan kajian-kajian kitab konservatif ini. Namun pada akhirnya, dengan mengaji dan mengkaji kitab kuning, nalar santri akan dibawa kepada realitas hidup yang ada.
Buku ini secara keseluruhan membincang situasi pesantren. Tentang aktivitas kepesantrenan, kaitannya dengan penguatan literasi. Memang, sejak saya nyantri dulu di Pondok Pesantren Annuqayah, dari bangun tidur hingga tidur lagi tidak lepas dari kegiatan pengembangan literasi. Tentu yang dimaksud adalah —sebagaimana Masdar Hilmy jelaskan— literasi dalam makna luas. Seluruh dimensi literal yang cakupannya pada seluruh kegiatan pengkajian dan pengajian. Tidak terbatas pada pola membaca dan menulis dalam arti sempit.
Islam secara umum —termasuk pesantren— telah berkontribusi dalam khazanah keilmuan dari berbagai aspek. Seperti dijelaskan oleh Alan Suud Maadi Menuju Peradaban Islam yang Kemilau dari Bilik Pesantren dengan Spirit Iqra, (hal. 25). Alan mengatakan bahwa pada masa keemasan Islam, ilmuwan Muslim punya peran besar dalam kancah keilmuan. Seperti al-Farabi yang dikenal sebagai filsuf, teolog, ilmuwan matematika, ahli politik dan kenegaraan, serta seniman; al-Battani yang terkenal dengan keahliannnya di bidang astronomi dan matematika; Ibnu Sina yang selain filsuf juga ahli pengobatan dan juga sastra.
Lalu ada Ibnu Batutah yang sangat terkenal dengan sebutan sang penjelajah dunia; Ibnu Rusyd seorang ahli al-Qquran, fisikawan, ahli matematika, ahli ilmu alam, astronomi, dan sebagai filsuf; al-Khawarizmi yang terkenal sebagai ahli matematika, astronom, astrolog, dan ahli geofrafi; Umar Khayam yang terkenal sebagai sastrawan yang menguasai matematika dan astronomi; Al-Ghazali yang filsuf, teolog, dan sufi; Ar-Razi yang ahli di bidang ilmu kedokteran, sains, dan filsuf. Dan deretan nama-nama lainnya yang tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai peletak pondasi keilmuan dari berbagai aspek.
Sementara, Arfan Hardiansyah dalam artikelnya “Tokoh Peradaban dari Pojok Tebuireng” (hal. 37) melihat kepesantrenan dari aspek tokoh KH Hasyim Asy’ari, pendiri organisasi terbesar di Indonesia: Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, KH Hasyim Asy’ari tidak perlu diragukan lagi dalam pergerakan kemerdekaan Indonesai. Melalui peristiwa revolusi jihad yang dilakukan oleh Beliau, dengan mengajak seluruh santri dan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Ada yang perlu diluruskan dalam artikel Arfan Hardiasyah ini, yaitu bahwa seharusnya Hari Santri Nasional jatuh pada tanggal 22 Oktober (Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, oleh Presiden Joko Widodo), bukan 22 November sebagaimana tertulis di artikel ini. Lebih dari itu, di artikel ini juga terdapat kerancuan paragraf (alinea tidak efektif) di paragraf pertama dan kedua halaman 39. Ada penyebutan KH Hasyim Asy’ari yang seharusnya KH Wahid Hasyim. Untuk membuktikannya, silakan pembaca menuju ke halaman tersebut.
Mohammad Hasan Basri dalam artikelnya di buku ini (hal. 40-44) menjelaskan tentang nama NU yang diambil dari sebuah kitab fenomenal, Al-Hikam, karya Ibn ‘Atha’ illah. “La tashhab man la yunhidluka haaluhu wala yadlulluka ilallahi maqaluhu; Janganlah engkau jadikan sahabat (guru) orang yang amalnya tidak membangkitkan kamu kepada Allah dan perkataannya tidak mengantarmu kepada Allah.” Disitir dari penjelasan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), bahwa kata “yunhidlu” yang bermakna membangkitkan, menjadi cikal bakal nama Nahdlatul Ulama (NU).
“Berawal dari Jurumiyah” adalah artikel Achmad Diny Hidayatullah (hal. 106-110), menjelaskan salah satu kitab kuning yang menjadi ciri pokok pesantren. Kitab Jurumiyah menjelaskan tentang kaidah penyusunan kalimat dan cara membacanya, yang dalam istilah pondok disebut Ilmu Nahwu. Kitab Jurumiyah merupakan dasar pengembangan ilmu kaidah Bahasa Arab (Ilmu Nahwu).
Secara makna kata, Jurumiyah artinya “mengalirlah (wahai) air!” Hal ini dinisbatkan pada sejarah pembuatan kitab tersebut oleh pengarangnya. Bahwa, ketika selesai ditulis, kitab Jurumiyah tersebut dihanyutkan ke sungai deras sambil mengatakan “jurumiyah“. Anehnya, tinta yang ada pada kitab tersebut sama sekali tidak luntur, tetapi tetap utuh sebagaimana adanya. Hal itu menjadi indikasi bahwa kitab tersebut mendapat ridha dari Allah. Terbukti, hingga saat ini kitab Jurumiyah menjadi kitab wajib di madrasah-madrasah dan berbagai pesantren.
“Kitab Al-Ajurumiyyah atau Jurumiyah yang dikarang oleh Abu Abdillah Sidi Muhammad bin Daud Ash-Shanhaji (w. 1324) konon setelah selesai dikarang, dibuang oleh pengarangnya. Doanya kepada Allah,”Ya Allah, jika saja karyaku ini akan bermanfaat, maka jadikanlah tinta yang aku pakai untuk menulis ini tidak luntur di dalam air.” (hal. 106).
Yoyok Amiruddin dalam artikelnya berjudul “Santri: Penggerak Khazanah Keilmuan“ lebih menekankan kepada karya tulis. Sebab, hanya dengan cara menulis, seseorang akan dikenang lebih kekal. “Perlu diingat, dengan menulis karya akan dikenang sepanjang masa. Karena budaya ini sudah mendarah daging di lingkungan pesantren. Budaya santri tidak hanya mengaji dan menulis, tapi juga mengkaji problematika masyarakat.”
Dalam pesantren sudah dibangun cara-cara mempertahankan nilai-nilai etika dan akidah. Dalam hal ini, Ahmad Wiyono menjelaskan,” Mempertahankan nilai-nilai (tradisi) pesantren, seperti kemandirian, keikhlasan, kesederhanaan, dan keteladanan, serta tradisi belajar mengajar dan kehidupan santri sehari-hari yang tawadlu’, qanaah, dan istiqamah yang merupakan aset moral untuk menghentikan penghancuran kemanusiaan (dehumanisasi).” (hal. 147).
Dan masih banyak lagi kepesantrenan, nilai-nilai pesantren, dan hakikat nyantri yang dapat diambil hikmahnya dari buku yang diterbitkan oleh CV Istana Agensi. Buku ini sangat pantas untuk disebut sebagai sastra pesantren, karena penulis dan kajiannya menggali tradisi kepesantrenan. Dalam pengantar penyunting (Muhammad Yunus) menjelaskan bahwa tujuan dari penerbitan “Aku, Buku, dan Peradaban” adalah sebagai bagian dari eksistensi sastra pesantren yang sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Pesantren telah berkontribusi nyata dalam khazanah literasi untuk peradaban.
Buku “Aku, Buku, dan Peradaban: Transformasi Pesantren Melalui Penguatan Literasi” (xx + 231 halaman; 155 x 230 mm) merupakan sebuah referensi yang pantas untuk kita baca. Muatan-muatan nilai kesantriannya begitu lekat. Karena, artikel-artikel dalam buku ini ditulis sesuai fakta dan pengalaman diri menjadi seorang santri. Sesuatu yang ditulis dengan nurani, maka jiwa kebenaran dan kesuciannya terpelihara dan dapat dijadikan teladan.
Akhir dari resensi ini, ingin saya kemukakan sebuah kaidah umum yang dijadikan semangat kepesantrenan dalam mewujudkan lembaga pendidikan yang dinamis-reformis. Hal ini juga dijelaskan oleh Nuchasanah Satomi dalam pengantarnya, yaitu, “Al-muhafadzatu ‘alal qadlimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah; mempertahankan hal-hal lama yang bagus dan menerima hal-hal baru yang lebih baik.” Wallahu A’ alam!