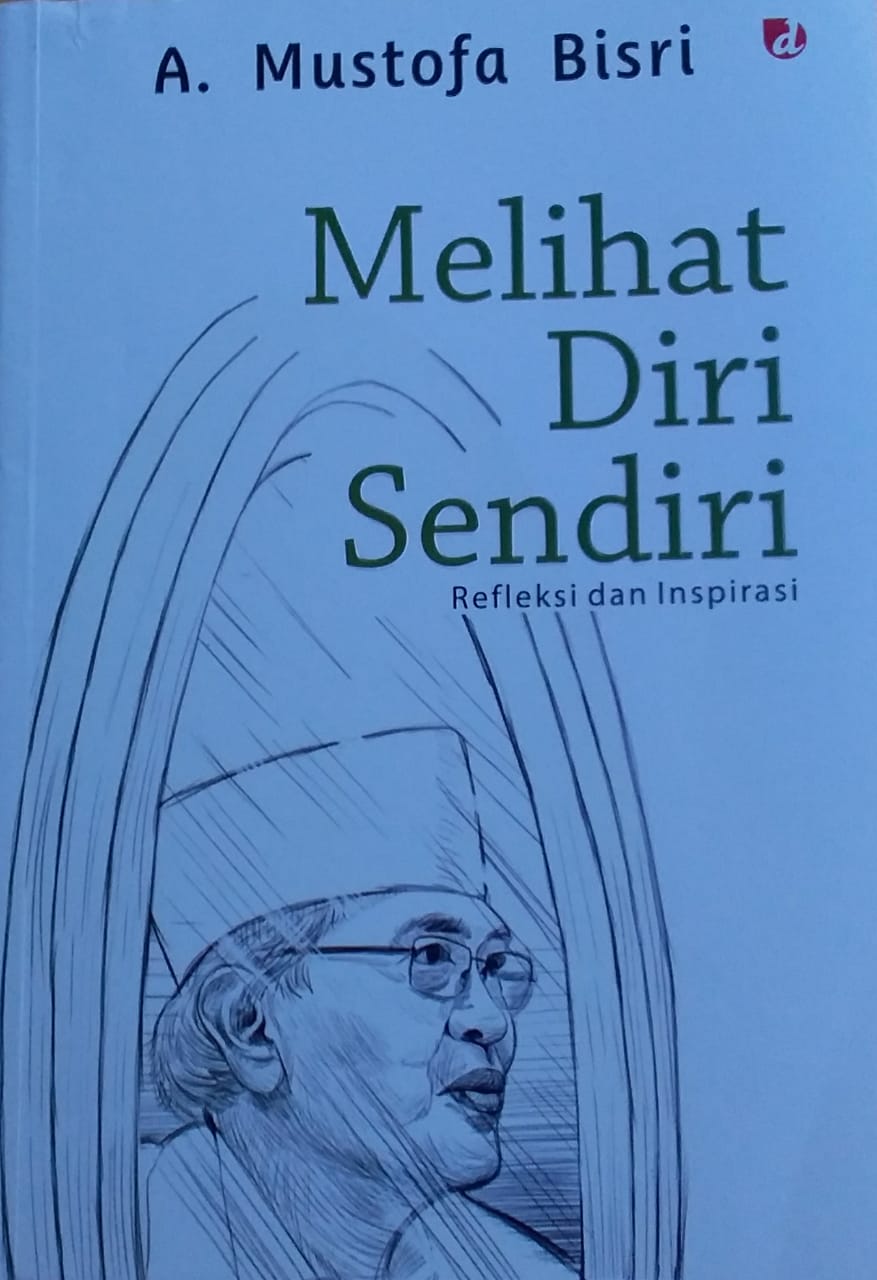A Mustofa Bisri atau yang biasa dipanggil Gus Mus adalah seorang penyair, kolomnis, kiai, dan pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang. Ia juga Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Tercatat juga sebagai deklarator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama Gus Dur. Bahkan, Gus Mus juga logo PKB tersebut.
Ulama besar ini telah banyak melahirkan buku. Salam satunya adalah yang berjudul Melihat Diri Sendiri. Buku ini merupakan kumpulan esai yang ditulis oleh Gus Mus, dan judul buku ini diambil dari salah satu judul esai tersebut.

Diawali sebuah kisah metafor, bahwa ada seorang bakhil —terlalu mencintai dunia dan dirinya sendiri—(hal. 268-273) yang dipanggil oleh seorang tokoh ulama ternama untuk menghadap. Saat itu, sang ulama merasa mendekati ajal. Memperoleh perlakuan “istimewa” tersebut, si bakhil merasa mendapat angin surga. Dan dalam hatinya yang congkak ia berkata bahwa apa yang dilakukannya selama ini mendapat apresiasi bagus dari seorang ulama.
Sesampainya di kediaman ulama tersebut, si bakhil bertanya (setelah banyak dialog untuk bercermin diri) dengan rasa waswas, “Wahai Tuan Syekh, apa gerangan? Mengapa Jenengan memanggil saya dan bukan yang lainnya?”
Jawaban kiai kharismatik berikut yang membuat si bakhil menjadi tersungkur dan menyadari kesalahannya selama ini. Sang ulama menjelaskan, “Karena setelah ajalku datang dengan takdir-Nya, aku masih akan bertemu dengan mereka di surganya Allah, sementara denganmu aku tidak akan berjumpa lagi kecuali kamu mampu mengubah perangaimu.”
Mendengar penjelasan ulama tersebut, si bakhil pun tertunduk dan tersungkur di tanah, dan mengakui kesalahannya serta bertobat dengan taubatan nashuha. Sebuah pengakuan dan penyesalan yang bernilai ibadah di sisi Allah, sehingga bagi orang yang bertobat disediakan ampunan yang paripurna (jannatul ma’wa).
Dari metafora tersebut, dipetik hikmah bahwa melihat diri sendiri merupakan diorama penyesalan terhadap sejarah diri. Dengan cara melihat diri sendiri, dari aspek ilmu pengetahuan maupun dari sisi religiusitas, akan membawa kepada pemahaman yang lebih baik. Tidak mudah menghakimi orang lain, tidak gampang menghina, dan tidak serta merta mengatakan bahwa orang lain salah dan yang benar hanya diri sendiri. Karena, seseorang yang merasa banar sendiri akan jatuh pada kesombongan dan congkak.
Buku Melihat Diri Sendiri ini kaya akan konsep dengan topik yang beragam. Sebagaimana Gus Mus jelaskan dalam pengantarnya (hal. 5-6) bahwa, “Buku ini merupakan kumpulan tulisan saya, yang saya kirimkan ke berbagai majalah dan koran antara lain Jawa Pos, Suara Merdeka, Tempo, Wawasan, Forum, dan entah apa lagi —saya lupa— dalam rentang waktu sejak ambruknya era Orde Baru.”
Jadi sudah jelas bahwa buku setebal 294 halaman ini mengandung khazanah pengetahuan yang meliputi berbagai persoalan.
Bercermin pada diri sendiri atas apa yang telah kita lakukan, sebagaimana juga Gus Mus ceritakan pada bagian Tokoh, saat Gus Mus dihukum oleh Kiai Ali, panggilan akrab Kiai Haji Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta, karena kakak Gus Mus tidak ikut mengaji. Dalam hati, Gus Mus berpikir sekaligus berontak, “Saya semakin tak mengerti: bagaimana bisa kakak saya yang tidak mengaji kok saya yang —ikut mengaji— dihukum. Aneh.”
Setelah melakukan “melihat diri sendiri” dengan cara tafakur dan perenungan, baru kemudian Gus Mus sadar, “Ternyata kesalahan saya memang besar. Saya buru-buru mengaji hingga lupa membangunkan kakak saya” (hal. 20).
Jadi, seorang pimpinan lembaga mempunyai cara sendiri untuk memberikan sanksi edukatif terhadap seorang santri. Dengan demikian, bukan tidak mungkin kakak Gus Mus merasakan penyesalan yang mendalam yang kemudian semakin giat dan peduli terhadap kewajiban belajar.
Dalam buku ini (hal. 25), Gus Mus juga mengisahkan tentang Mbah Dullah yang mempunyai perhatian lebih terhadap masyarakat sekitar. Saking berlebihannya, hingga Mbah Dullah tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Hingga pada suatu waktu, Gus Mus mengajukan pertanyaan bagaimana caranya menolak undangan masyarakat yang sangat bajibun. Mbah Dullah menjawab, “Tetapkan tarif yang sangat tinggi, niscaya mereka tidak akan lagi mengundangmu.”
Namun, untuk melakukan saran tersebut, Gus Mus merasa tidak mungkin. Karena Mbah Dullah bukan A Mustofa Bisri, “Berbeda dengan Mbah Dullah yang sudah tidak peduli dengan penilaian orang, yang penting penilaian Allah,” begitu kata Gus Mus beralasan (hal. 25).
Ini pentingnya melihat diri sendiri dengan kemampuan dan pemahaman yang ada. Bukan kemudian merasa sanggup terhadap apa yang dilakukan orang lain, senyampang orang lain tersebut bisa niscaya tidak sama kedekatannya dengan kita, yaitu kedekatan kepada Allah.
Sementara pada esai lainya, Gus Mus menjelaskan hubungannya dengan makanan. Seringkali kita baca di berbagai media sosial, netizen yang mempersoalkan halal dan harammya suatu zat makanan. Sementara, mereka abai bagaiman makanan itu diperoleh. Apakah dengan cara halal (legal) atau sebaliknya, haram.
Dalam konteks ini, Gus Mus mengatakan, “Orang sibuk dengan hal haramnya makanan, tetapi tidak mempedulikan halal haramnya cara mendapatkan makanan itu sendiri” (hal. 65).
Itu artinya bahwa kita harus sama-sama mawas diri terhadap segala persoalan demi terciptanya kedamaian. Baik kedamaina yang bersifat ilahiyah (terkait ibadah) maupun kedamaian terkait dengan kehidupan sosial (komunikasi dalam kehidupan). Jika hal ini telah menjadi kebiasaan, maka kehidupan yang tentram dan damai akan kita jalani hingga akhir kehidupan.
Berikutnya yang sempat menjadi catatan saya adalah tentang niat dalam melakukan suatu perbuatan. Dalam hal ibadah, niat menjadi legalitas agar ibadah yang kita kerjakan bernilai maqbul di sisi Allah.
Dalam hal ini, Gus Mus memberikan contoh sederhana dengan mengatakan, “Membaca al-Quran dengan niat mendapat piala, tentu tidak sama dengan niat mendapat pahala.” Lebih jelas dapat dibaca dalam buku ini dengan judul “Taat, Ibadah, dan Taqarrub” (hal. 72).
Sebenarnya masih banyak lagi esai A Mustofa Bisri yang dapat dibaca di dalam buku ini. Terkait dengan berbagai aspek kehidupan. Berkenaan dengan topik keseharian. Sehingga, bagi pembacanya, buku ini akan menambah khazanah pengetahuan terapan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik kehidupan secafa vertikal maupun sosial horizontal kemasyarakatan.
Buku ini benar-benar recomended untuk dijadikan refrensi pengetahuan. Sebab, selain pembahasannya yang sangat jelas, bahasa yang digunakan pun sangat indah dan mudah dipahami. Oleh sebab itu, memiliki buku ini sangat direkomendasikan baik sebagai pribadi maupun untuk perpustakaan di lembaga pendidikan.
“Man ‘arofa nafsahu faqad arofa Robbahu. (Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka sungguh menegnal Tuhannya!)”
Saya tidak menemukan kelemahan dalam buku ini, kecuali terdapat typo atau salah ketik pada tulisan al-Quran dalam aksara latin, misal “wadlkhuli” yang pertama seharusnya tertulis “fadlkhuli” menggunakan huruf fa’ (hal. 48). Satu lagi yang menjadi “catatan” dalam buku terbitan Diva Press ini, yaitu lafal-lafal al-Quran ditulis dengan huruf latin, bagi yang kurang terbiasa cara membacanya sedikit menggangu dan merepotkan.
Selebihnya, buku ini pantas dibaca oleh siapa saja (tanpa batasan umur). Karena, melihat diri sendiri dengan membaca buku ini adalah membaca diri A Mustofa Bisri. Ada kenikmatan tersendiri membaca artikel Gus Mus, karena penulis yang juga penyair ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh banyak orang. Tidak menggunakan bahasa populer yang mendakik-dakik yang (terkadang) justru sulit dipahami oleh pembaca. Wallahu A’lam!
Identitas Buku
Judul : Melihat Diri Sendiri
Penulis : A. Mustofa Bisri
Editor : Anwar
Tata Sampul : Ferdika
Tata Isi : Ika Setiyani
Penerbit : DIVA Press Yogyakarta