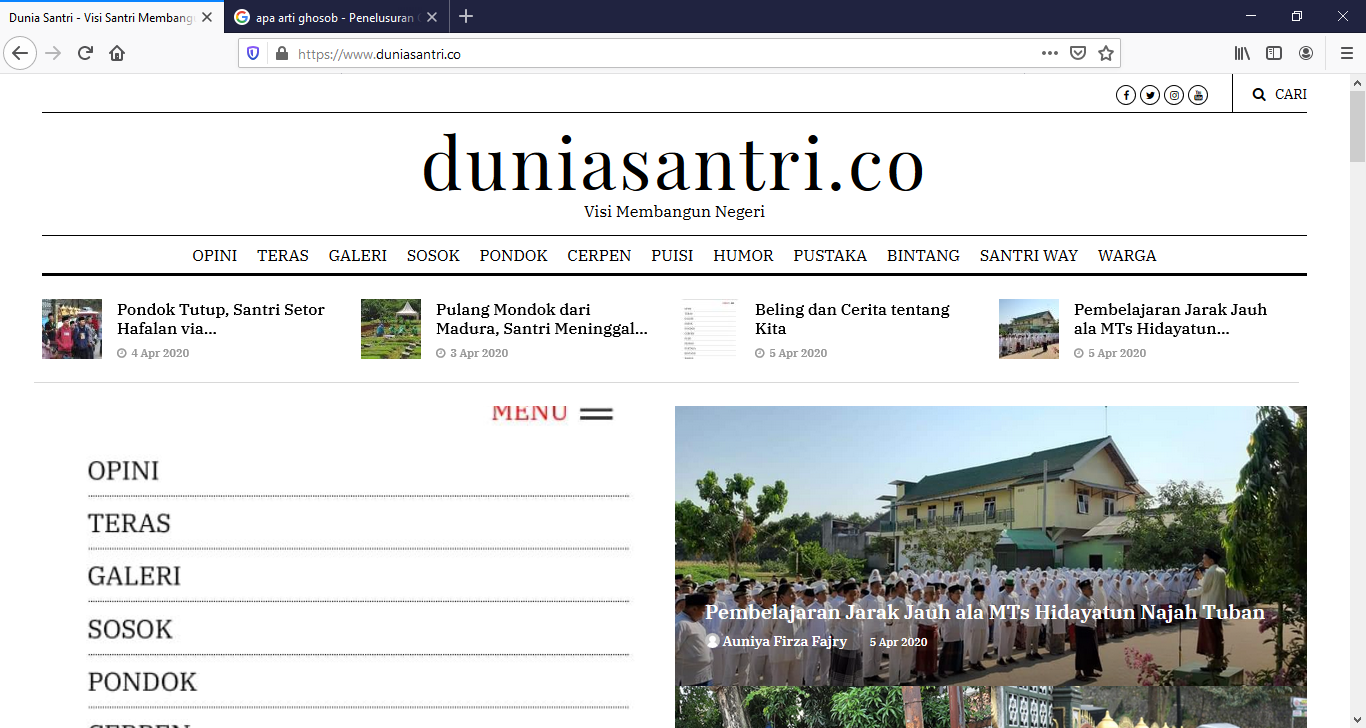Seperti biasanya, pada Minggu pagi di pondok diadakan roan, kerja bakti bersih-bersih di lingkungan pesantren. Ada santri yang kebagian mengepel musala, menyapu halaman, menguras dan membersihkan jeding, menyapu ruang-ruang kelas, mencabuti rumput-rumput liar, dan, tentu saja, membersihkan bilik masing-masing.
Saya bersama seorang teman santri memilih menyapu dan mengumpulkan sampah-sampah tak jauh dari tempat pembuangan sampah. Tanpa dinyana, entah dari arah mana datangnya, Pak Kiai sudah berada di samping saya. Kami langsung membungkuk memberi hormat, tentu saja dengan rasa cemas dan waswas kalau-kalau…

Tiba-tiba Pak Kiai menunjuk tanah, “Coba itu kamu ambil.”
Kami saling menoleh bingung. Di atas tanah yang ditunjuk Pak Kiai hanya ada beling, pecahan bohlam atau lampu listrik. “Ya, itu… beling itu,” kata Pak Kiai saat saya mencoba memungutnya.
Beling itu pun saya serahkan kepada Pak Kiai, teman saya diam membatu. Kini beling itu ada di tangan Pak Kiai, ditimang-timang sebentar, lalu diserahkan kembali pada saya. “Makanlah,” perintah Pak Kiai sambil tersenyum.
“Lah, apa salah saya pagi-pagi sudah dihukum, disuruh sarapan beling,” kata saya dalam hati dengan tubuh gemetar. Teman saya kian membatu.
Seakan tahu kegalauan dan ketakutan yang saya rasakan, Pak Kiai menepuk bahu membesarkan hati saya. “Makanlah. Kamu sudah bisa memakannya,” Pak Kiai mengulang perintahnya, tetap dengan tersenyum.
Samina wa athona, krek-krek-krek…, saya pun memakannya. Masyaallah, dalam sekejap beling itu hancur, menjadi tepung, menjadi bubur di mulut saya. Jadilah, pagi itu saya sarapan bubur beling.
Pak Kiai tersenyum sambil sekali lagi menepuk bahu saya, “Sudah tambah satu lagi ilmumu.” Saya masih terdiam takjub. “Asal kamu mampu menjaga diri, tetap menjalani hidup bersih, ilmu itu tak akan hilang,” kata Pak Kiai sambil berlalu.
Sampai beberapa tahun kemudian, sesekali saya masih mencoba “mengunyah” beling dan, alhamdulillah, dengan krek-krek-krek beling-beling itu menjadi tepung. Tapi, sekarang, jangankan menggigitnya, sekadar membayangkannya pun sudah tak berani lagi. Anda pasti tahu kenapa….