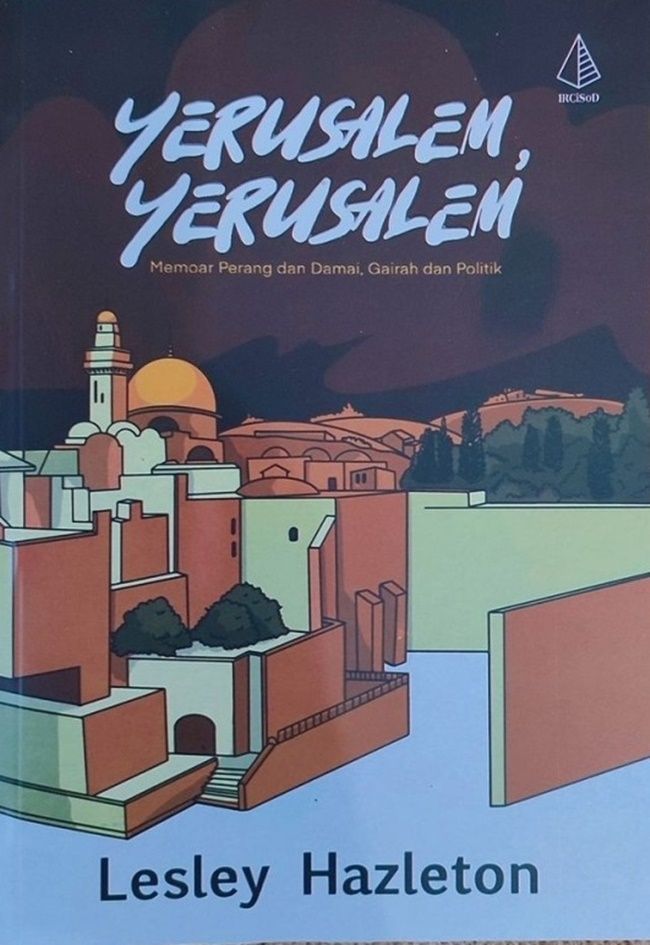Kota itu berdiri di atas lapisan-lapisan waktu, seperti cat yang menutupi tembok tua: tak ada satu pun yang benar-benar terhapus. Ia dikenal sebagai kota suci, tapi kesucian di sana terasa seperti retakan yang terus menganga.
Di sinilah Lesley Hazleton menuliskan Yerusalem, Yerusalem, bukan sebagai jurnalis yang melaporkan, bukan pula sebagai sejarawan yang mencatat. Ia menulis sebagai seseorang yang pernah hidup di dalam tubuh kota itu—dan keluar darinya dengan luka yang tak bisa disembuhkan.

Dalam buku ini, tidak ada klimaks, tidak ada simpulan. Hanya gerak maju dan mundur dari kenangan yang berat. Hazleton datang ke Yerusalem untuk tinggal sementara, tapi ia menetap lebih dari satu dekade. Ia tidak menulis tentang kota itu dengan jarak. Ia menulis dengan napas yang masih terengah, dengan pandangan yang sudah buram karena terlalu lama menatap api dari dekat.
Yerusalem yang ditulis Hazleton bukan Yerusalem dari brosur wisata atau laporan diplomatik. Ia adalah Yerusalem yang sesak oleh ideologi, yang pekat oleh iman, yang setiap lorongnya menyimpan bisik-bisik pengakuan dan pengkhianatan. Kota tempat agama menumpuk, dan mungkin karena itu juga tempat cinta dan kebencian sulit dibedakan.
Hazleton mencatat sesuatu yang penting: bahwa Yerusalem bukan hanya tempat tinggal para manusia yang percaya, tapi juga tempat tinggal para manusia yang menuntut. Kesucian bukanlah karunia, melainkan klaim. Dan setiap klaim, pada akhirnya, menuntut pengorbanan. Di kota ini, seseorang bisa berdoa dengan khusyuk di pagi hari, lalu melempar batu di sore harinya. Antara iman dan amarah, hanya dibatasi oleh jalan setapak.
Kesucian yang Menuntut Korban
Ada satu kesunyian yang terasa di halaman-halaman buku ini: semacam kelelahan. Kelelahan karena menyaksikan kota yang terus menuntut kesetiaan mutlak, dan tak pernah memberi ruang bagi keraguan. Hazleton bertemu dengan orang-orang yang dulu lembut, lalu menjadi militan. Ia melihat bagaimana keyakinan, bila dibiarkan berjalan tanpa pengawasan, bisa berubah menjadi topeng kekuasaan.
Dan mungkin, Yerusalem memang tak pernah adil terhadap mereka yang ragu. Di kota ini, keraguan adalah dosa. Ia tidak punya tempat di antara tembok ratapan, masjid-masjid tua, atau gereja-gereja bersejarah. Di tempat ini, orang hanya boleh percaya, atau keluar. Hazleton memilih keluar. Tapi sebelum itu, ia menulis.
Hari ini, Yerusalem kembali menjadi halaman depan. Dentuman masih terdengar, meski sering kali dibungkam oleh istilah-istilah yang tampak netral: “operasi militer,” “perlindungan warga sipil,” “hak membela diri.” Tapi kota itu tahu: kata-kata bisa berbohong, dan luka tetap terasa nyata.
Perang yang terjadi sejak 2023 di Gaza, dan ketegangan yang menjalar hingga Yerusalem, membuat kita kembali bertanya: berapa lama lagi kota ini bisa bertahan tanpa hancur oleh hasrat orang-orang yang mengaku mencintainya? Sebab seperti cinta yang posesif, kasih sayang yang terlalu mutlak pun bisa mencekik.
Hazleton, dalam tulisannya yang tenang tapi menusuk, sebenarnya sudah memberi peringatan. Ia tidak menunjuk siapa yang salah, karena dalam konflik yang begitu panjang dan rumit, menunjuk seringkali hanya membuat jari kita sendiri terluka. Ia hanya mencatat perubahan—dan dari catatan itulah kita bisa meraba: kota ini tidak sedang menuju kedamaian, melainkan sedang mencari alasan baru untuk kembali bertengkar.
Kota yang Menggantung di Antara Waktu
Yerusalem yang sekarang bukanlah kota dari masa lalu. Tapi ia belum menjadi kota masa depan. Ia tergantung di antara dua kutub waktu: selalu ingat, tapi sulit berubah. Dan mungkin, seperti kata seorang penyair yang pernah singgah di kota itu, “Yerusalem bukan untuk didiami, tapi untuk diimani.” Kalimat itu terdengar indah, sampai kita menyadari: iman yang terlalu absolut bisa menjadi alasan untuk membakar rumah orang lain.
Ada bagian yang paling getir dalam buku Hazleton: ketika ia menyadari bahwa di Yerusalem, bahkan ruang kosong pun bisa diperebutkan. Bukan karena tanah itu subur, tapi karena tanah itu punya sejarah. Di kota lain, rumah bisa menjadi tempat tinggal. Di Yerusalem, rumah bisa menjadi simbol. Dan simbol selalu punya harga, yang sering dibayar dengan kehidupan.
Hazleton tidak mengakhiri bukunya dengan harapan besar. Ia hanya menutup pintu dan berjalan pergi. Tapi buku ini tetap terbuka—seperti luka yang belum sempat dijahit. Ia menulis bukan untuk mengajak, tapi untuk mengingatkan. Bahwa di tempat di mana kesucian diklaim terlalu sering, yang tinggal hanyalah keheningan yang getir.
Yerusalem mungkin akan tetap seperti ini: kota yang mendoakan dan membakar. Kota yang tak bisa ditinggalkan, tapi juga tak bisa dihuni sepenuhnya. Di sana, langit terlalu dekat, dan bumi terlalu padat. Mungkin itu sebabnya banyak orang kehilangan arah: terlalu sibuk menatap ke atas, dan lupa menengok mereka yang terluka di bawah.
Dan seperti Hazleton, kita pun hanya bisa membaca. Mungkin itu cara paling manusiawi untuk tetap peduli tanpa ikut membakar. Mungkin itu satu-satunya cara untuk mencintai kota yang bahkan tak bisa mencintai dirinya sendiri.
Data Bukan:
Judul: Yerusalem, Yerusalem; Memoar Perang dalam Damai, Gairah, dan Politik
Penulis: Lesley Hazleton
Penerbit: IRCiSoD
Tahun Terbit: 2022 (edisi terjemahan Bahasa Indonesia)
Isi: 306 halaman
ISBN: 978-623-5348-18-6