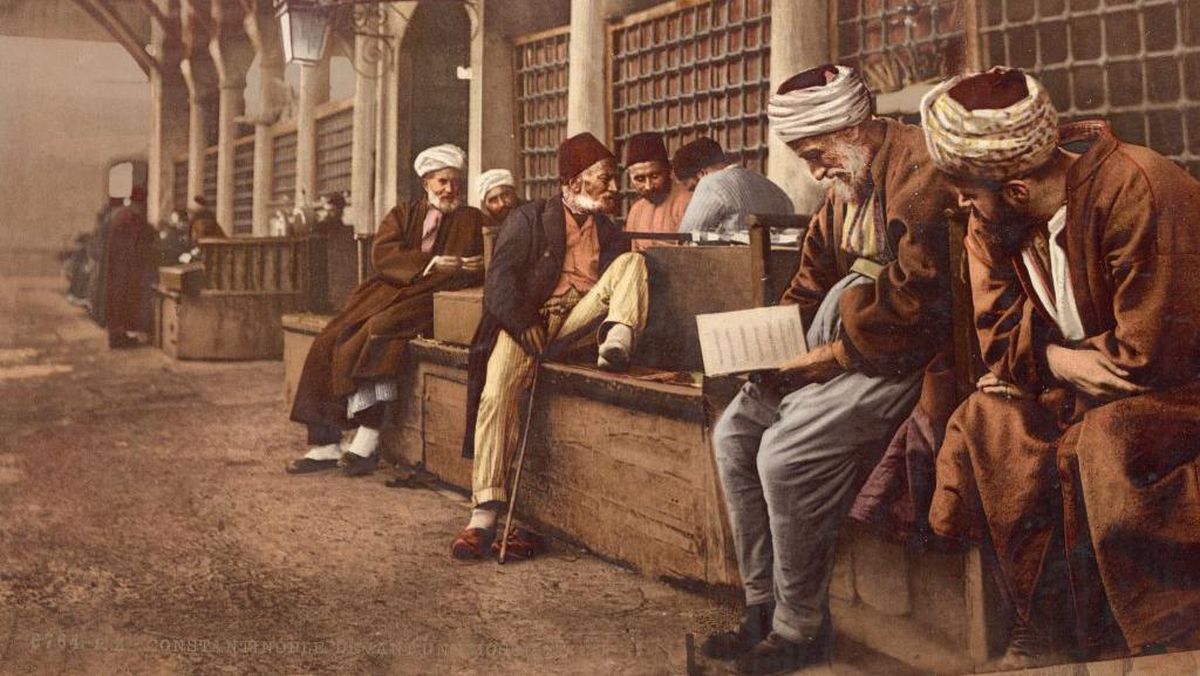Islam adalah agama yang komprehensif dan universal. Ia menyentuh setiap ranah kehidupan manusia tanpa terkecuali. Ranah sosial, individual, dan transendental tidak dapat lepas dari peran Islam sebagai agama yang komprehensif. Tujuan utama dari misi mulia ini adalah menjaga lima hal pokok yang tingkat urgensinya sangat tinggi, yaitu agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta.
Tujuan mulia tersebut dibungkus dalam hukum Islam yang bersumber dari nash-nash syari’i. Nash-nash syar’i tersebut mengalami suatu proses yang panjang agar kompleksitas problematika kehidupan dapat terjawab olehnya. Proses tersebut membawa suatu perubahan dan perkembangan dari hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam yang melewati zaman dan tempat yang berbeda akan membawa corak yang juga beragam.

Pada mulanya, hukum Islam tumbuh dan lahir pada masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Ia mendapatkan wahyu dan petunjuk dari Allah SWT.
Namun, setelah wafatnya sang pembawa risalah, berhenti pula wahyu yang turun dari Allah SWT berupa ayat-ayat Al-Qur’an. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi generasi setelah Rasulullah dalam menyikapinya. Mereka melakukan ijtihad, menggali hukum, agar nash-nash syar’i tersebut dapat memberikan solusi yang aplikatif dalam menjawab tantangan perubahan zaman.
Masa Pembinaan
Fase pembinaan, atau fase pertumbuhan dalam beberapa literatur, terjadi pada masa kenabian Rasulullah SAW. Pada masa ini wahyu dan hadis turun beriringan dengan realita sosial masyarakat yang masih belum terlalu kompleks.
Proses tasyri’ dilakukan secara berangsur-angsur agar tidak terjadi gelombang gejolak yang begitu besar karena masyarakat Arab pada masa itu sangat berpegang teguh pada tradisi kultural dan spiritual mereka. Kebijakan ini yang kemudian mampu mengetuk hati masyarakat Arab pada masa itu dan menjadikan Islam mulai diterima secara sukarela.
Penyampaian dakwah Islamiyah yang ditebar oleh Rasulullah SAW bersandar pada instruksi langsung dari Allah SWT. Lima ayat pertama surah al-‘Alaq turun memberi sinyal bahwa ia akan menjadi penutup para nabi dan rasul.
Ia mulai menyampaikan dakwahnya ketika instruksi dari Allah turun kepadanya yang berisi mandat untuk memberikan peringatan kepada kerabat terdekatnya. Ia berhasil mengajak orang-orang terdekatnya untuk memeluk agama Islam dengan sukarela.
Di antara mereka yang menerima ajakannya untuk memeluk agama Islam pada masa awal-awal kenabian ini adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah; Zaid bin Haritsah, bekas budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah; Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah; dan Abu Bakar, sahabat terdekat Rasulullah.
Abu Bakar termasuk sahabat yang paling banyak menuangkan kontribusinya bagi perkembangan agama Islam. Relasi yang ia bangun berhasil mengantarkannya untuk mengajak mereka memeluk Islam seperti dirinya.
Beberapa Sahabat yang memeluk Islam melalui Abu Bakar adalah Sa’d bin Abi Waqqash, Zubair bin Awwam, dan Usman bin Affan. Para pelopor inilah yang disebut dalam Surah at-Taubah ayat 100 sebagai as-Sabiqun al-Awwalun.
Realita historis mencatat adanya periodisasi penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam melalui dua periode dengan karakteristiknya masing-masing. Periode pertama adalah periode Makkah. Periode ini berlangsung selama kurang lebih 13 tahun dan menekankan proses tasyri’ pada aspek tauhid dan akhlak. Konstruksi iman yang kokoh didahulukan agar basis fundamental seorang hamba menjadi kuat dan tidak mudah goyah.
Tasyri’ pada aspek fiqh (hukum Islam) belum diberlakukan secara tegas karena adanya indikasi bahwa Islam masih belum lepas dari perlakuan represif kaum kafir Quraisy dan faktor-faktor lainnya. Aspek fikih yang ditegakkan pada periode ini hanya mencakup ranah ibadah. Sedangkan ranah jihad, hudud, qishash, dan lain sebagainya masih belum dapat ditegakkan secara kaffah (sempurna). Realita yang terjadi pada periode ini merupakan salah satu indikasi nyata keadilan Allah SWT.
Periode kedua adalah periode Madinah. Periode ini berlangsung selama kurang lebih 10 tahun pasca hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke Yatsrib, nama asli kota Madinah.
Pada periode kedua ini, proses tasyri’ menekankan pada aspek fikih. Penegakan hukum Islam berjalan beriringan dengan realita sosial karena basis tauhid telah mengakar kuat pada periode sebelumnya. Iklim kultural yang hangat juga menjadi faktor pelicin diberlakukannya hukum Islam secara kaffah.
Aspek-aspek fikih selain ibadah mendapatkan tempat yang sesuai pada periode ini. Pada periode ini, sistem hukum Islam mulai menampakkan cahayanya walaupun belum mengalami kodifikasi.
Sumber utama hukum Islam pada periode ini adalah Al-Qur’an dan hadis. Rasulullah dalam menghadapi suatu problematika menunggu instruksi dari Allah melalui wahyu Al-Qur’an. Jika terdapat kekaburan makna dalam ayat Al-Qur’an, ia sendiri yang akan menafsirkannya seperti pada surah al-An’am ayat 82 (H.R. Al-Bukhari Nomor 3175). Dalam beberapa kasus ia memutus suatu kasus berdasarkan ijtihadnya seperti pada peristiwa Perang Badar (Miskan: 2021).
Para Sahabat pada masa kenabian juga melakukan ijtihad independen. Mereka berpedoman para Al-Qur’an dan hadis Rasulullah ketika permasalahan dalam Al-Qur’an menuntut penjelasan.
Kisah terkenal tentang ijtihad sahabat Amr bin Ash yang mengganti mandi junub dengan tayamum. Ia berdalil dengan ayat Al-Qur’an yang melarang untuk membunuh diri sendiri karena pada waktu itu udara malam sangat dingin. Ketika berita itu disampaikan kepada Rasulullah, ia malah tertawa dan tidak mengatakan apa pun (Suharto: 2021).
Masa Pengembangan
Fase atau masa ini dimulai setelah wafatnya Rasulullah. Wafatnya Rasulullah juga beriringan dengan berhentinya proses tasyri’. Hal ini ditandai dengan sempurnanya ayat-ayat Al-Qur’an yang turun dan hadis-hadis Rasulullah. Dalam waktu yang bersamaan, realita sosial yang dihadapi umat Islam makin kompleks karena jarum jam peradaban yang terus berputar maju. Problematika yang dihadapi pun beragam coraknya sehingga menuntut digali dan ditemukannya hukum yang dapat menjawab dan menyuguhkan solusi. Para Sahabat mengambil peran kunci yang sangat krusial pada masa ini.
Para Sahabat adalah generasi yang paling memahami nash-nash syar’i karena mereka berada pada masa yang sama dengan proses tasyri’ itu sendiri. Kedekatan mereka dengan Rasulullah juga menambah nilai lebih dalam menyingkap makna ayat-ayat Al-Qur’an. Penguasaan terhadap teks dan konteks membantu mereka dalam menggali hukum dalam menjawab masalah-masalah praktis kontemporer. Meluasnya teritorial kekuasaan Islam pada masa ini menjadi salah satu faktor meningkatnya kompleksitas problematika yang dihadapi umat Islam.
Masa pengembangan ini melalui setidaknya masa empat al-Khulafa` al-Rasyidun. Pertama, masa Abu Bakar (632-634 M). Pada masa pemerintahan Abu Bakar, kebijakan khalifah tercurah pada peredaman pemberontakan seperti pemberontakan yang dipantik oleh kaum murtad dan para nabi palsu.
Namun, dalam beberapa kasus tercatat bahwa pernah ada ijtihad di bidang fikih, terutama waris. Kasus tersebut berkaitan dengan apakah seorang nenek mendapatkan bagian waris atau tidak. Abu Bakar tidak menganggap adanya bagian bagi nenek. Namun, Mughirah bin Syu’bah dan Muhammad bin Maslamah mengatakan ada hadis yang menyatakan bahwa nenek mendapatkan bagian seperenam (Sopyan: 2018, 87).
Pada masa ini juga Al-Qur’an dibukukan untuk pertama kalinya atas inisiasi Umar. Pengumpulan Al-Qur’an tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah, tetapi itu tetap dilakukan demi kemaslahatan.
Kedua, masa Umar bin Khattab (634-644 M). Pada masa Umar, perluasan teritorial Islam terjadi secar masif. Islam mulai menyentuh wilayah Mesir, Persia, Syam, dan lain sebagainya.
Makin luasnya teritorial Islam tersebut berimplikasi pada kompleksitas problematika yang dihadapi. Ada sebagian problematika tersebut yang tidak ditemukan solusinya secara eksplisit dari Al-Qur’an maupun hadis. Ada juga yang solusinya ditemukan dalam Al-Qur’an dan hadis, tetapi diperlukan interpretasi kontekstual agar nash tersebut dapat menjawabnya dengan solutif. Hal ini diaplikasikan dalam suatu kasus ketika terjadi wabah kelaparan dan terjadi pencurian. Umar tidak menerapkan had (sanksi pidana Islam) pada pelakunya.
Ketiga, masa Utsman bin Affan (644-657 M). Beberapa bentuk ijtihad Utsman antara lain adalah: (a) penyeragaman bacaan Al-Qur’an dalam satu mushaf yang disebut Mushaf Usmani. Naskah-naskah Al-Qur’an yang berbeda dibakar sebagai bentuk penghormatan dan penjagaan kepada bacaan Al-Qur’an yang asli; (b) Dilaksanakannya azan salat Jumat selama dua kali. Pertimbangan yang digunakan adalah agar azan tersebut merata ke seluruh negeri (Sopyan: 2018, 93-94).
Keempat, masa Ali bin Abi Thalib (656-660 M). Beberapa ijtihad pada masa Ali adalah sebagai berikut: (a) penetapan dera bagi pemabuk adalah 80 cambukan; (b) pemberian simbol dalam Al-Qur’an berupa titik agar mempermudah orang-orang Ajam (non-Arab) ketika membaca Al-Qur’an (Sopyan: 2018, 95).
Masa Pembukuan
Fase ini dimulai pada masa tabiin sekitar tahun 100 H sampai dengan tahun 300 H. Pada periode ini, Islam sudah menyebar ke seluruh jazirah Arab sebagai hasil dari upaya perluasan wilayah dakwah Islam yang dilakukan sejak masa Khulafaur Rasyidin dan dilanjutkan oleh tabiin.
Sejalan dengan perluasan wilayah Islam ini, muncul kota-kota penting yang memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan ilmu fikih dan ushul fikih. Kota-kota tersebut secara geografis terbagi tiga yaitu Irak (Kufah dan Basrah), Hijaz (Mekkah dan Madinah), dan Syria.
Pada periode ini muncul perbedaan pendapat yang disebabkan perbedaan geografis atau karena masuknya unsur-unsur lokal yang mewarnai keputusan atau fatwa hukum. ‘
Urf atau praktik adat kebiasaan setempat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam keputusan hukum yang mereka hasilkan. Perbedaan tersebut akhirnya mengerucut pada munculnya dua macam corak atau aliran fikih yang disebut madrasah ahl al-ra`y dan madrasah ahl al-hadis. Perbedaan dua kelompok atau madrasah ini lebih didasarkan kepada kecenderungan dalam melakukan ijtihād.
Ahl al-ra`y adalah kelompok yang dominan dalam penggunaan logika (ra`y) dalam berijtihad. Madrasah ahl al-ra`y dimotori oleh Abdullah bin Mas’ud (w. 32 H/653 M) yang berpusat di Kufah.
Kufah adalah sebuah kota metropolis yang di dalamnya terjadi asimilasi kebudayaan masyarakat antara Islam dengan budaya Persia. Di kota ini muncul banyak sekali problematika kontemporer yang lebih kompleks. Sementara jumlah hadis yang beredar sedikit karena terbatasnya jumlah Sahabat di wilayah ini.
Menurut aliran ini nash-nash syar’i terbatas, sedangkan peristiwa yang terjadi di masyarakat senantiasa berkembang dan terkadang baru, tidak ada ketentuannya dalam nash-nash syar’i. Untuk peristiwa baru seperti ini maka harus dilakukan ijtihād dengan ra`y.
Di samping itu, menurut pendapat mereka penetapan hukum syara’ itu pasti ada ilat (sebab/alasan) tertentu dan untuk tujuan tertentu. Para ulama tugasnya adalah menemukan ilat tersebut yang selanjutnya dapat digunakan untuk memecahkan persoalan yang ada. Imam mazhab yang termasuk dalam aliran atau corak madrasah ahl al-ra`y ini adalah imam Abu Hanifah (w. 148 H/767 M).
Kelompok kedua adalah madrasah ahl al-ḥadīṡ, tokohnya adalah Said Musayyib al-Makhzumi (w. 94 H/715 M) yang berpusat di Hijaz.
Para Sahabat yang tinggal di Hijaz jauh lebih banyak daripada yang hidup di Kufah, sehingga jumlah hadis yang beredar jauh lebih banyak dan sangat mudah ditemukan. Sementara di sisi lain, munculnya permasalahan baru tidak banyak dan tidak begitu kompleks sebagaimana yang terjadi di Kufah.
Masyarakat Hijaz adalah masyarakat yang memiliki tradisi keislaman yang kuat yang sudah terbentuk sejak masa Nabi. Aliran ini banyak diikuti oleh imam mazhab antara lain Imam Malik (w. 179 H/800 M), al-Syafi’i (w. 204 H/819 M), Ahmad bin Hanbal (w. 241 H/855 M), dan Daud al-Zahiri (w. 883 M).
Menurut aliran ini penetapan hukum didasarkan pada sumber pertama, yaitu wahyu atau Al-Qur’an dan hadis. Jika dalam wahyu tidak ditemukan, maka selanjutnya dicari pendapat para Sahabat Nabi. Jika dalam ketiga sumber tersebut tidak ditemukan dasarnya maka baru dibolehkan penggunaan ra’y.
Pada fase ini telah dimulai gerakan pembukuan fikih, sunnah, dan ilmu-ilmu lainnya. Para imam mazhab mengembangkan formulasi teori-teori ijtihād yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum baru. Karena itu mereka dianggap sebagai peletak dasar ushul fikih. Misalnya, Imam Abu Hanifah menciptakan teori istiḥsān dan ‘urf. Sedangkan, Imam Malik mensistematisasikan maṣlaḥah mursalah atau istiṣlāḥ.
Upaya formulasi dan sistematisasi ilmu ushul fikih dilakukan lebih serius oleh Imam al-Syafi’i dengan menulis kitab al-Risālah. Ini merupakan kitab ushul fikih pertama yang berisi kaidah-kaidah ushul yang telah diterapkan oleh para Sahabat, Tabiin, dan imam-imam mazhab sebelumnya. Atas prestasinya ini, Imam al-Syafi’I dianggap sebagai “Bapak Ushul Fikih” (Farid: 2020, 23-24).
Daftar Pustaka
al-Bukhari. (n.d.). Shahih al-Bukhari. Maktabah Syamilah.
Farid, A. (2020). USHUL FIKIH KELAS X MA PEMINATAN KEAGAMAAN. Kementerian Agama RI.
Miskan, H. S. (2021, April 17). Diakses dari suara muhammadiyah: https://web.suaramuhammadiyah.id/2021/04/17/peran-abu-bakar-dalam-perang-badar-dan-pelajaran-dibaliknya/
Sopyan, Y. (2018). Tarikh Tasyri’ Sejarah Perkembangan Hukum Islam. Depok: Rajawali Pers.
Suharto, Y. (2021, Juli 2021). Retrieved from nu online: https://nu.or.id/syariah/nabi-pun-tertawa-saat-sahabat-mengimami-shalat-usai-junub-dan-tayamum-rCmWP
Syaibah, I. A. (n.d.). Mushannaf Ibnu Abi Syaibah. Maktabah Syamilah.