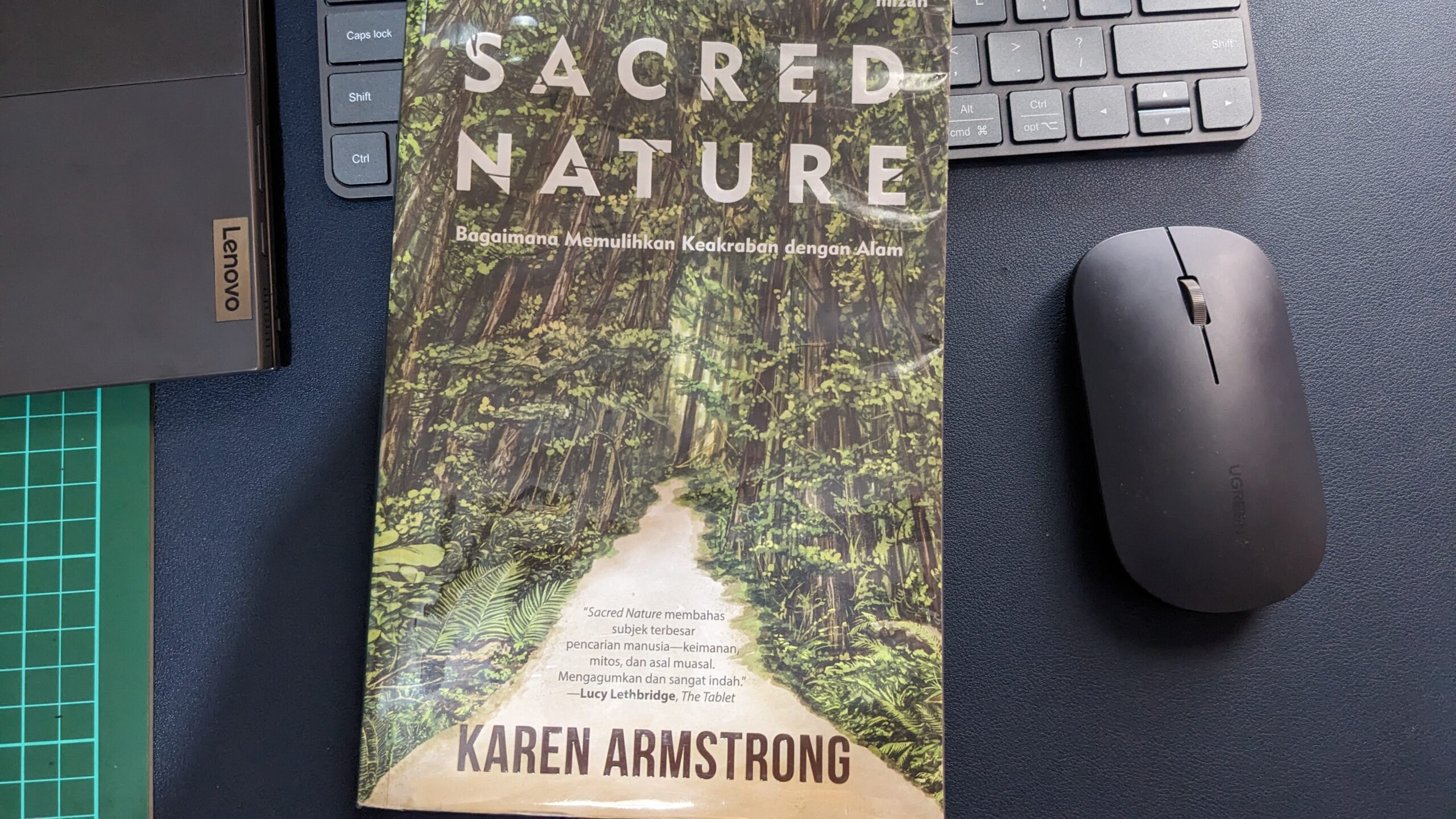Buku ini saya beli tepat di bulan terbit versi terjemahannya yang diterbitkan oleh Mizan. Saya sedikit beruntung karena membelinya saat momentum Borobudur Writer & Cultural Festival yang saat itu membahas tema besar tentang lingkungan.
Judul buku ini sangat lugas dan padat, Sacred Nature, dan ditulis oleh seorang humanis bernama Karen Amstrong. Sekilas, mungkin ia bisa dibilang pendatang baru dalam menulis soal lingkungan; pertama, Karen Amstrong adalah seorang pemikir yang selama ini menulis di wilayah agama-agama dunia, terutama monoteis, dan seluruh dunia mengakui kepakarannya di wilayah itu. Kedua, wacana lingkungan ini terbilang baru dari wacana-wacana global yang telah ada.

Namun, mungkin, berangkat dari latar itu, Karen Amstrong justru melihat agama-agama memiliki tanggung jawab besar pada wacana besar lingkungan yang muncul dan mengemuka di abad ini.
Buku Sacred Nature ini secara format lebih sebagai kumpulan esai, namun tetap jadi sehimpun dalam tema utuh perihal lingkungan. Berbeda dengan cerpen yang dihimpun lebih sporadis dalam kumpulan cerpen (kumcer). Namun secara prinsipil, keduanya (kumpulan esai/cerpen) memiliki kemiripan; buku Sacred Nature ini layaknya berkebun di pekarangan rumah (meminjam analogi Haruki Murakami dalam menulis cerpen) yang bisa saja ditulis (ditanam) seketika, berbeda dengan menulis buku atau novel (masih dalam ungkapan Haruki Murakami), yaitu seperti berkebun di ladang yang membutuhkan perencanaan, kalkulasi, dan waktu yang panjang.
Penilaian subjektif saya pada Karen Amstrong yang dikemukakan di awal sebagai pendatang baru dalam menulis isu lingkungan, agaknya memang tidak begitu berlebihan. Dalam buku ini Karen Amstrong menulis dengan kekayaan yang telah dimilikinya dalam studi agama: ia mengekstraksi seluruh ajaran agama-agama tentang alam dan penciptaan yang sakral; mulai dari kisah Adam, ajaran-ajaran para guru mistik (master of reality) di dunia Timur, dan dalam Islam yang banyak merujuk pada kisah Ayub serta beberapa filsuf serta mistikus Islam pasca abad pertengahan di Eropa seperti Ibn Arabi.
Dengan demikian, Karen Amstrong memilih menulis dengan tidak menggunakan analisa serta data saintifik sebagaimana para ilmuwan dan ahli lingkungan kontemporer dalam menulis soal lingkungan. Karen Amstrong memilih menulis dengan gayanya sendiri yang menggabungkan kekuatan ekplanasi logika dengan bentangan metafisika agama-agama, namun dengan hal ini membuat karya ini menjadi unik dan lebih menarik.
Di bagian prolog dan awal bab, Karen Amstrong banyak mengungkap metafisika dunia Timur yang membawa alam suci transendental bisa menyatu dengan kehidupan bumi yang profan. Hal demikian, bagi pembaca Barat, akan dinilai menjadi pandangan hidup yang monistik dan panteistik.
Meskipun, bagi pembaca Islam, hal tersebut berbeda dan dapat dibantah, karena di bagian tengah buku (bab 3) hingga akhir, Karen Amstrong banyak mengelaborasi perihal pengurbanan, kekudusan Tuhan (Allah) yang terjaga di luar nalar yang bisa dijangkau oleh manusia. Ditambah pula, di bab-bab bagian akhir, Karen Amstrong mengelaborasi pemikiran filsuf dan mistikus Islam seperti Ibn Arabi yang jelas-jelas berbeda dengan gagasan monisme dan panteisme dalam memandang kesatuan alam.
Di lembar awal buku, Karen Amstrong membuka dengan ungkapan puisi seorang guru mistik Asia bernama Timur Zhang Zai:
Langit adalah ayahku
Bumi adalah ibuku
Dan bahkan mahkluk kecil seperti diriku
Menemukan tempat hangat di antara keduanya.
Maka, apa-apa yang mengisi semesta
Kuanggap tubuhku
Dan apa-apa yang mengarahkan semesta
Kuanggap alamku
Semua manusia adalah saudaraku, dan
Semua yang ada (di alam) sahabat-sahabatku.
Puisi tersebut mewakili ajaran-ajaran para filsuf mistik di Asia Timur yang lebih dekat pada tradisi monistik: Zen Budhis, konfusius, hingga Jalan Dao dalam ajaran Laozi.
Namun, pada kesimpulannya, ajaran-ajaran tersebut memiliki kesamaan dalam memandang kesatuan alam. Satu di antaranya apa yang disebut wanwu (hal-hal), yaitu “kita harus memperlakukan seluruh yang ada di alam, sebagaimana kita sendiri ingin diperlakukan, sehingga kita bisa berbagi daya hidup yang sama dan terhindar dari kerusakan (hlm, 35).”
Hampir di setiap bab dalam buku ini, Karen Amstrong mengawalinya dengan ungkapan “Jalan ke Depan”. Saya menangkapnya sebagai visi dari kekudusan ajaran-ajaran agama yang telah dielaborasi dan diekstraksi. Artinya, visi dari agama tersebut berbeda dengan para ilmuwan futuristik yang melawat dan menanggalkan masa lalu untuk menuju masa depan. Ia telah menghilangkan elemen terdasar alam semesta dalam keteraturannya yang mengandung paradoks.
Sementara, Jalan ke Depan dalam agama-agama justru berbalik arah ke belakang sebagai caranya bergerak; artinya, ia telah menyadari dan menerima elemen terdasar dari alam semesta, yaitu paradoks yang justru sebagai elemen penggerak keteraturan, dan terciptanya keharmonisan hidup itu sendiri.
Dengan makna lain, selama kita tidak menyadari dan menerima paradoksal alam dunia, kita akan terjebak pada kebenaran yang seolah bertentangan satu sama lain.
Satu hal yang menjadi poin penting dan ditekankan dari keseluruhan bab dalam buku ini adalah penghormatan kepada alam. Karen Amstrong menilai hilangnya penghormatan pada alam seiring dengan penghormatan manusia pada manusia itu sendiri.
Agama (Abrahamik) secara gamblang memberi keterangan sejak awal penciptaan Adam, bahwa Bumi ini diciptakan untuk manusia, namun bukan berarti manusia adalah yang paling berhak atas segala isinya. Manusia merupakan mahkluk Tuhan di Bumi yang diberi akal, namun sekaligus menghimpun keseluruhan elemen Bumi.
Dalam pengertian lain, manusia pada dasarnya memiliki elemen yang sama sebagaimana tumbuhan dan hewan. Perbedaannya, manusia memiliki akal budi dan jiwa. Perbedaan akal budi dan jiwa inilah yang menjadikan manusia memiliki fungsi lebih agung dari hewan dan tumbuhan. Sebab, akal budi ada untuk menjaga keteraturan semua elemen-elemen Bumi agar tetap terus terjaga.
Hal tersebut kemudian yang mendasari para teoritikus etika lingkungan (environmental ethics) di era kiwari, yaitu ingin mengembalikan hal itu, bahwa alam; pohon, sungai, laut, tumbuhan, hewan, dan sebagainya memiliki hak sebagaimana manusia yang hidup atas kebutuhan darinya. Maka bersikap hormat pada alam akan mengembalikan manusia akan penghormatan pada dirinya sendiri (kemanusiaan).
Dalam konteks itulah agama memiliki andil besar secara teleologis sejak awal penciptaan Adam, dan masih akan relevan dalam menyeru umat manusia yang berakal budi untuk bersikap hormat pada alam, sebagaimana ia sebagai manusia ingin dihormati.
Sebagai penutup, penghormatan pada alam di abad sebelum modern sebenarnya sudah terjadi di hampir semua kebudayaan. Terlebih di Indonesia, penghormatan itu bahkan sudah dipertemukan antara agama (Islam) dan budaya melalui beragam ekspresi selametan atau syukuran.
Artinya, di Indonesia ritual penghormatan pada alam sudah masuk pada wilayah inti dari ajaran agama untuk mengesakan Tuhan (tauhid) lewat jalan tradisi atau pembiasaan. Yang menjadi problem hari ini, tradisi itu tergerus oleh kehidupan modern dan perlahan hilang karena tidak dimengerti oleh nalar modern.
Maka untuk memulihkan manusia dan alam, alih-alih melakukan pemulihan alam yang rusak oleh eksploitasi kapital, Karen Amstrong justru mengajak untuk lebih mengakrabi diri sebagai langkah awal memulihkan dan memahami alam itu sendiri.
Data Buku:
Judul: Sacred Nature
Penulis: Karen Armstrong
Penerbit: Mizan Pustaka
Tanggal Terbit: 4 Mei 2023
ISBN: 9786024413095
Isi: 180 Halaman