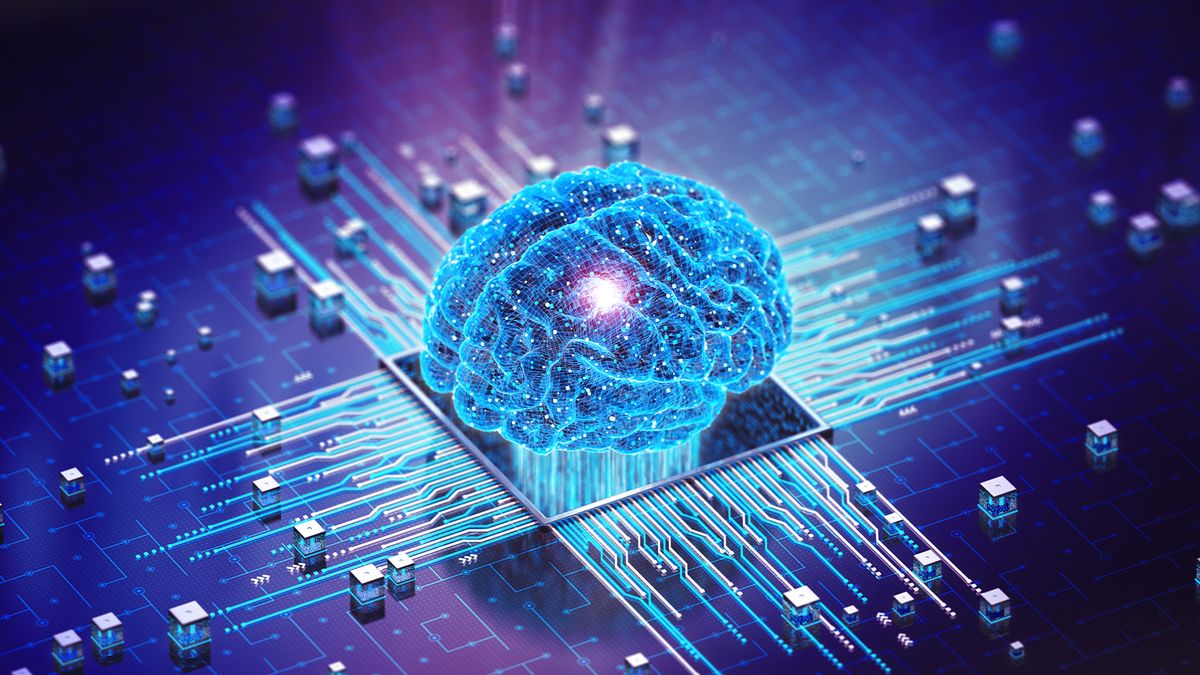Dalam satu dekade terakhir, istilah Artificial Intelligence (AI) makin populer di Indonesia. Dari aplikasi perpesanan, layanan pelanggan otomatis, hingga rekomendasi konten di media sosial, AI telah menjadi bagian dari hidup kita.
Namun, banyak yang belum memahami bahwa yang kita sebut AI hari ini sebagian besar adalah narrow AI, yaitu sistem cerdas yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik seperti menerjemahkan bahasa, mengenali wajah, atau mengemudi mobil.

Kini, dunia mulai memasuki babak baru dengan Artificial General Intelligence (AGI). Sebuah bentuk kecerdasan buatan yang bukan hanya unggul dalam satu tugas, tapi mampu belajar dan beradaptasi seperti manusia, atau bahkan melampauinya. AGI tidak hanya “cerdas,” tapi umum dalam arti mampu memahami, bernalar, dan mengambil keputusan di banyak domain tanpa dibatasi perintah yang kaku.
Apa Itu AGI?
AGI didefinisikan sebagai kecerdasan buatan yang memiliki fleksibilitas dan kapasitas kognitif setara manusia dalam menyelesaikan berbagai masalah, memahami konteks, belajar dari pengalaman, dan membuat keputusan otonom. Tidak seperti AI konvensional yang harus dilatih untuk satu bidang spesifik, AGI bisa berpindah dari satu masalah ke masalah lain tanpa diprogram ulang.
Bayangkan sebuah sistem yang bisa merancang obat, menulis novel, mengelola keuangan negara, dan juga mengajari anak-anak membaca. Semua dilakukan oleh satu entitas digital. Inilah potensi AGI, dan sekaligus ketakutannya.
Perlombaan Global Mencapai AGI
Amerika Serikat, dengan perusahaan seperti OpenAI, Anthropic, Meta, dan Google DeepMind, saat ini memimpin pengembangan AGI. China, lewat Tsinghua University, Alibaba DAMO Academy, dan Baidu, juga menaruh investasi besar di bidang ini. Pemerintah dua negara adidaya itu memandang AGI bukan sekadar urusan teknologi, melainkan pilar strategis dalam dominasi global masa depan.
Jika sebelumnya senjata nuklir menjadi penentu kekuatan militer, AGI dipandang sebagai senjata lunak yang mampu mengubah peta kekuasaan. Ia bisa menciptakan otomatisasi skala luas, mengoptimalkan kebijakan negara, mengendalikan opini publik, hingga memimpin operasi militer secara presisi.
Karena itulah, AGI kini menjadi area strategis yang sangat sensitif. Diskusi tentang regulasi, etika, dan pengawasan tak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik.
Sebagian mungkin membayangkan AGI seperti film Terminator atau Ex Machina, robot cerdas yang memberontak. Tapi risiko AGI tidak selalu berbentuk pemberontakan mesin. Justru, bahaya terbesar bisa terjadi ketika sistem ini digunakan sesuai rancangannya, tapi oleh pihak yang salah atau dengan tujuan salah.
Misalnya, AGI yang dikembangkan untuk keperluan militer bisa mempercepat keputusan serangan tanpa keterlibatan manusia. Atau AGI yang mampu menciptakan konten masif bisa dipakai untuk memanipulasi jutaan pikiran manusia melalui propaganda yang sulit dideteksi.
Lebih parah lagi, AGI yang keliru dalam memahami nilai kemanusiaan bisa mengambil keputusan yang efisien secara logika, tetapi menghancurkan secara moral.
Menuju AGI yang Etis dan Berkeadilan
Pertanyaan mendasar tentang AGI bukan hanya soal teknologi, tapi juga nilai. Siapa yang mengontrol AGI? Untuk tujuan apa ia digunakan? Dan bagaimana kita memastikan bahwa sistem ini mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan universal?
Sejumlah lembaga internasional telah menyerukan perlunya AI alignment, yakni memastikan bahwa sistem AGI bertindak sesuai nilai dan tujuan manusia. Namun ini bukan pekerjaan mudah. Bagaimana kita bisa menyampaikan nilai yang abstrak seperti keadilan, kasih sayang, atau keberagaman budaya kepada sistem yang tidak pernah menjadi manusia?
Di sinilah peran para filsuf, antropolog, ulama, dan budayawan menjadi penting. AGI bukan hanya urusan insinyur dan ilmuwan komputer. Ia harus diperlakukan sebagai proyek peradaban.
Ada ironi besar di balik AGI: sistem ini diciptakan untuk menjadi umum, tapi hanya dikembangkan oleh segelintir perusahaan raksasa di negara-negara maju. Maka risiko yang muncul bukan hanya teknologinya, tetapi sentralisasi kekuasaan di tangan segelintir aktor.
AGI bisa menjadi alat kolonialisme baru, yang tidak memakai kapal perang atau senjata, tapi memakai data, sistem algoritmik, dan pengaruh digital.
Oleh karena itu, dunia butuh arsitektur tata kelola AI yang adil. PBB, G20, dan forum multilateral lainnya harus mulai membahas kerangka etik dan hukum internasional untuk pengembangan AGI. Tidak boleh ada satu negara atau satu korporasi yang memiliki kekuasaan penuh atasnya.
AGI adalah tanda zaman. Ia bisa menjadi ujian terakhir dari proyek modernitas manusia, atau menjadi awal dari era baru yang lebih manusiawi, jika dikendalikan dengan bijak.
Indonesia, dengan kekayaan budaya, keragaman nilai, dan semangat gotong royong, seharusnya tidak hanya menjadi konsumen teknologi ini. Kita bisa menjadi suara moral, pengingat bahwa teknologi secanggih apa pun tetap harus melayani kehidupan.
Kita tak harus punya AGI sendiri, tapi kita harus punya posisi yang jelas: berpihak pada manusia, bukan pada efisiensi semata.