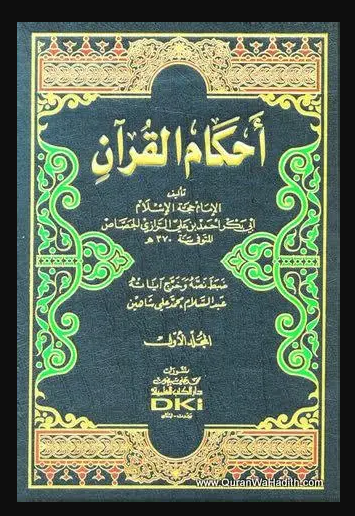Abū Bakar Aḥmad bin ʿAlī al-Rāzī, yang lebih dikenal dengan sebutan al-Jaṣhaṣh, merupakan seorang mufasir dengan posisi penting sebagai pakar fikih dalam kerangka pemikiran mujtahid. Karya tafsirnya yang terkenal, Ahkām al-Qur`ān, merupakan eksplorasi metodologis terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an.
Tulisan ini mengacu pada pendekatan deskriptif-analitis untuk mengungkap metode tafsir al-Jaṣhaṣh yang cenderung menekankan pada penalaran serta komparasi antar-teks. Tafsirnya dikategorikan sebagai tafsir tahlili dengan metode muqāran. Ini metode yang membandingkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, serta pendapat ulama, dan disusun berdasarkan urutan mushaf.

Corak yang mendominasi karya ini ialah fikih, karena seluruh pembahasannya berkutat pada hukum-hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an.
Perjalanan al-Jaṣhaṣh
Abū Bakar Aḥmad bin ʿAlī al-Rāzī, yang lebih dikenal dengan gelar al-Jaṣhaṣh, memperoleh laqab tersebut berdasarkan profesinya. Istilah al-Jaṣhaṣh sendiri berasal dari kata yang menunjuk pada pekerjaan sebagai tukang kapur atau pelapis dinding. Dalam sumber lain, ia merujuk pada profesi sebagai tukang cat.
Ia dilahirkan di kota Rayy, Irak, pada tahun 305 Hijriah. Pada usia 19 tahun, yakni sekitar tahun 325 H, ia merantau ke Baghdad guna mencari ilmu. Perjalanan keilmuannya tidak berhenti di sana. Ia kemudian melanjutkan studi ke Ahwaz, sebuah daerah yang kala itu menjadi pusat keilmuan penting. Setelah menyelesaikan pencariannya di Ahwaz, ia kembali ke Baghdad dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Naisabur. Di sana, ia belajar di bawah bimbingan al-Ḥākim al-Naisābūrī yang memiliki pandangan keilmuan serupa dengan gurunya terdahulu, Abū Ḥasan al-Karkhī.
Dalam proses belajarnya, al-Jaṣhaṣh berguru pada beberapa tokoh ulama besar seperti Abū Sahl al-Zujāj, Abū Saʿīd al-Būrdāʾī, dan lainnya. Ia dikenal luas sebagai ulama fikih terkemuka dalam mazhab Ḥanafī, sekaligus sebagai pribadi yang zuhud dan wara. Al-Jaṣhaṣh wafat di Baghdad pada hari Ahad, 7 Zulhijjah tahun 370 H, meskipun terdapat pendapat lain yang menyebutkan ia wafat pada tahun 376 H.
Ketokohan dan keluasan ilmunya sempat mengantarkannya pada berbagai tawaran jabatan sebagai qāḍī (hakim), namun semuanya ia tolak. Alasannya, ia berkomitmen menjalankan hidup secara zuhud dan menjauh dari urusan duniawi. Sekembalinya dari Naisabur ke Baghdad pada tahun 344 H, gurunya, Abū Ḥasan al-Karkhī, telah wafat pada tahun 340 H (952 M).
Dalam proses belajarnya, al-Jaṣhaṣh tidak hanya fokus pada satu bidang saja. Ia juga mempelajari ilmu fikih dan hadis secara mendalam. Di antara guru-gurunya dalam bidang fikih adalah Abū Sahl al-Zujāj, Abū Saʿīd al-Būrdāʾī, Mūsā ibn Nāṣir al-Rāzī, Abū al-Ḥasan al-Karkhī. Sedangkan, dalam bidang hadis, ia belajar kepada ʿAbd al-Baqī ibn Qāniʿ. Adapun, di antara murid-murid yang meneruskan ilmunya ialah: Abū ʿAbdillāh Muḥammad ibn Yaḥyā al-Jurjānī dan Abū al-Ḥasan Muḥammad ibn Aḥmad al-Zaʿfarānī.
Al-Jaṣhaṣh juga dikenal produktif dalam menulis. Selain tafsir Aḥkām al-Qurʾān, ia menyusun berbagai karya penting yang menjadi rujukan dalam mazhab Ḥanafī, di antaranya Aḥkām al-Qurʾān, Syarḥ Mukhtaṣar al-Karkhī, Syarḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī, Syarḥ al-Jāmiʿ Muḥammad ibn al-Ḥasan, Syarḥ al-Asmāʾ al-Ḥusnā, dan Ādāb al-Qaḍāʾ.
Contoh Penafsiran
Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an, Abū Bakar Aḥmad bin ʿAlī al-Rāzī al-Jaṣhaṣh menyampaikan pemahaman yang mendalam terhadap makna dan isi kandungan ayat. Ia menunjukkan dedikasi intelektual yang tinggi melalui kecermatan dalam menelaah pesan-pesan yang terkandung dalam teks Al-Qur’an. Sebagai seorang fukaha yang memiliki kedudukan ilmiah yang tinggi, ia mengedepankan peranan rasionalitas dalam menafsirkan teks, meskipun tetap merujuk pada Al-Qur’an dan hadis sebagai dasar utama meski dalam porsi yang terbatas.
Hal tersebut tampak dalam tafsirnya terhadap ayat-ayat seperti dalam surah al-Baqarah, di mana ia memberikan penjelasan secara rinci dan kritis terhadap keabsahan makna ayat. Selain itu, ia juga mengutip syair-syair klasik Arab sebagai pendekatan linguistik dan interpretatif. Hal ini menunjukkan bahwa metode tafsirnya melibatkan perpaduan antara dalil naqli dan argumentasi aqli, termasuk analisis perbandingan antara ayat, hadis, syair, dan akal.
Kecenderungan al-Jaṣhaṣh terhadap mazhab Ḥanafī sangat kuat. Ini menjadi salah satu ciri khas dalam penafsirannya. Ia sering kali menyelaraskan interpretasi ayat-ayat hukum dengan prinsip-prinsip fikih mazhab tersebut. Pendekatannya memperlihatkan pembelaan tegas terhadap pandangan fikih Ḥanafī, sebagaimana terlihat dalam tafsirnya terhadap ayat:
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
Artinya: “Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam” (Q.S. al-Baqarah [2]: 187)
Melalui ayat ini, al-Jaṣhaṣh menekankan kewajiban menyempurnakan puasa hingga waktu malam, tidak hanya dalam konteks puasa wajib tetapi juga puasa sunah. Penafsirannya menyoroti sisi literal (ẓāhir) ayat, yang menunjukkan bahwa seseorang yang telah memulai puasa sunah, maka ia wajib menyelesaikannya sampai matahari terbenam.
Penyusunan tafsir oleh al-Jaṣhaṣh dilandasi oleh keinginannya untuk mengaitkan antara ushul fikih dan tauhid dalam memahami hukum-hukum Al-Qur’an. Tafsir hukum sendiri telah berkembang dari corak riwayah ke corak ma’tsur dan al- ra’yi, dan al-Jaṣhaṣh termasuk dalam arus rasional yang tetap merujuk pada otoritas Al-Qur’an dan sunnah. Ia mengikuti metode dan pandangan mazhab Ḥanafī secara konsisten, sehingga tafsirnya mencerminkan ideologi fikih tersebut.
Metodologi dan Sistematika
Al-Jaṣhaṣh menggunakan metode muqāran dan tahlili. Dalam metode ini, ia tidak hanya membahas kandungan ayat satu per satu, tetapi juga membandingkan ayat-ayat, hadis, dan pendapat ulama untuk memperkuat interpretasi hukumnya. Ia menggunakan pendekatan sistematik khas fikih: setiap topik dalam tafsirnya disusun menyerupai kitab fikih klasik, seperti pembahasan wudhu, salat, zakat, dan lainnya. Sumber rujukannya meliputi Al-Qur’an, hadis, serta pandangan ulama terdahulu.
Penafsiran al-Jaṣhaṣh dikenal dalam menafsiri kitab yang terdapat pada tiga hal, yakni sistematika mushafi, nuzuli, dan maudhu’i. Dalam mushafi, penafsiran memperhatikan tertib susunan ayat serta surat dalam Al-Qur`an, diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas. Dalam nuzuli, penafsiran dilakukan dengan mengurutkan turunnya surat-surat Al-Qur`an, seperti yang telah dilakukan Muhammad `Izzah Darwazah dalam tafsirnya al-Tafsir al-Hadis dengan menggunakan sistematika nuzuli. Adapun, dalam maudhu’i, penafsiran terhadap Al-Qur`an berdasarkan dengan tema tertentu dan mengelompokkan ayat yang memiliki hubungan serta topik tertentu.
Al-Jaṣhaṣh juga menganalisis ayat Al-Qur`an dari keahliannya serta memaparkan dari hasil analisisnya secara terperinci dan melebar. Seperti ketika ia menafsiri pada surat al-Fatihah ayat pertama. Pada awalnya al-Jaṣhaṣh menjelaskan dari segi kebahasaan. Setelah itu ia memberi penjelasan dari segi hukum bacaan basmalah walaupun lafaz tersebut di ucapkan ketika salat, ataupun bacaan surat. Sebagian ia juga mendalami dengan hasil riwayat-riwayat dari para sahabat dan tabiin.
Diterangkan dalam kitab Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum, bahwa Muḥammad Alī Ayazi berpendapat, penafsiran al-Jaṣhaṣh terlalu berlebihan dalam aspek pembahasan hukum. Seperti halnya ia mencantumkan permasalahan fikih yang seharusnya tidak terdapat dalam kitab tafsir, sebagaimana perbedaan argumen pada kalangan ulama fikih. Bukan hanya akan hal itu, akan tetapi membandingkan dari masing-masing pandangan ulama fikih seperti akan kitab fikih. Sebagian yang terdapat dalam tafsirnya juga terdapat pembahasan yang tidak ada hubungannya dengan ayat tersebut, dan jikalau terhubung itu juga sangatlah jauh. Al-Dzahabi dalam hal ini mengungkapkan bahwa tafsir karya al-Jaṣhaṣh lebih sama dengan buku fikih al-Muqarrān.
Menurut pandangan Mannā al-Qaṭṭān, al-Jaṣhaṣh menafsirkan ayat-ayat al-ahkam yang sangat ekstrem. Juga ketika menyanggah seseorang yang tidak sepemiikiran dengannya. Al-Jaṣhaṣh juga terlalu berlebihan dalam mentakwil ayat Al-Qur`an yang menyebabkan para pembaca enggan akan meneruskan bacaannya. Sebab ungkapan-ungkapan yang menyinggung mazhab lain sangatlah kritis.
Contoh penafsirannya yang dianggap terlalu memaksakan ayat yang tidak seharusnya masuk dalam konteks permasalahan fikih ada dalam surah Yusuf [12]:26
قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
Untuk membela dirinya, Yūsuf berkata, “Istrimulah yang memintaku dan berusaha memperdayaku.” Keduanya saling melempar tuduhan. Kemudian salah seorang dari keluarga bertindak sebagai penenang atas permasalahan tersebut dan mengatakan, “Jika baju gamisnya koyak di muka, maka pengakuan wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta.
Ayat tersebut sudahlah jelas akan kisah pribadi Nabi Yūsuf yang menyinggung keterkaitan dengan seorang wanita. Namun dalam penafsiran ini, al-Jaṣhaṣh menyangkutkan permasalahan harta temuan.
Sikap kritis terhadap Muawiyah dalam tafsirnya, al-Jaṣhaṣh menyiratkan bahwa kepemimpinan yang sah hanyalah milik Khulafāʾ al-Rāsyidīn. Ia menolak legitimasi Muawiyah karena tidak termasuk golongan yang berhijrah. Hal ini menunjukkan preferensi ideologis al-Jaṣhaṣh terhadap para khalifah awal yang dipandang sebagai pemimpin yang adil dan religius.
Sementara itu, tafsir al-Jaṣhaṣh juga menunjukkan kecenderungan rasionalis yang dekat dengan aliran Muʿtazilah. Hal tersebut terlihat pada penafsirannya terhadap QS. al-Baqarah:102 dan QS. al-Anʿām:103. Ia memahami konsep sihir sebagai hal yang tidak nyata dan menyatakan bahwa Allah tidak dapat dilihat oleh mata, yang merupakan pandangan khas rasionalis.
Keunggulan dan Kekurangannya
Keunggulan tafsir al-Jaṣhaṣh terletak pada ketajaman analisis, kedalaman argumen, serta struktur yang sistematis. Ia juga menggabungkan pendekatan tekstual dan rasional secara seimbang. Namun, keterikatannya yang kuat terhadap mazhab Ḥanafī membuat tafsirnya terkadang menampilkan bias dan ketidaktoleransian terhadap mazhab lain, yang bisa menimbulkan ketegangan antarpandangan. Maka dari itu Al-Jaṣhaṣh dapat disebut sebagai mufasir dan fakih besar yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan tafsir hukum Islam. Karyanya Ahkām al-Qur’ān menampilkan corak fikih yang kuat dengan struktur penulisan yang sistematis dan analitis. Meskipun terdapat kekurangan, kontribusinya terhadap literatur tafsir tetap menjadi rujukan penting dalam studi hukum Islam klasik.