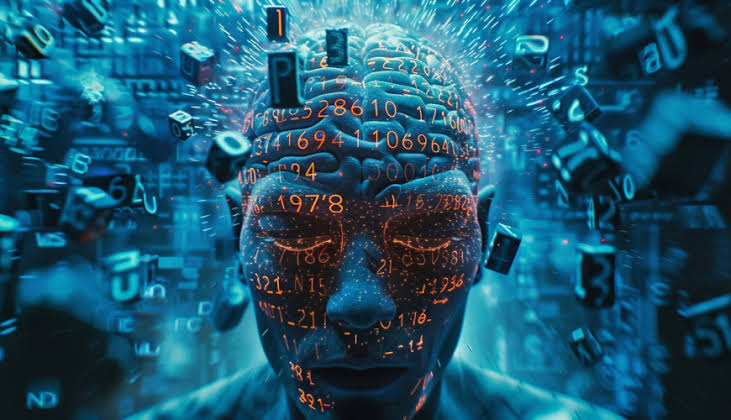Agama, dalam perjalanan sejarah peradaban manusia, selalu memainkan peran sentral dalam membentuk nilai, norma, dan struktur sosial. Ia bukan semata sistem kepercayaan terhadap realitas metafisik, tetapi juga sebagai fondasi etis yang membimbing manusia dalam menghadapi kompleksitas kehidupan.
Namun di era digital—di mana kehidupan manusia mulai tenggelam dalam algoritma, data, dan ilusi konektivitas global—agama dihadapkan pada tantangan baru: bagaimana tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman yang tidak lagi tunduk pada logika moral konvensional?

Kemajuan teknologi digital, terutama internet, kecerdasan buatan (AI), dan media sosial, telah mengubah secara radikal cara manusia berinteraksi, berpikir, bahkan memahami realitas. Transformasi ini tidak bersifat kosmetik, melainkan struktural.
Dalam konteks tersebut, pendekatan keagamaan yang bersifat moralistik dan individualistik saja menjadi tidak lagi memadai. Agama tidak cukup hanya mengingatkan umat untuk “berakhlak baik” di dunia maya; ia harus mampu memetakan persoalan sistemik yang membuat ruang digital begitu rentan terhadap kekerasan simbolik, polarisasi, dan manipulasi kebenaran.
Kita sering kali terjebak pada pandangan bahwa teknologi bersifat netral; bahwa ia hanya sebagai alat, tergantung pada siapa yang menggunakannya. Narasi ini tidak hanya naif, tetapi juga berbahaya. Sebab, teknologi digital saat ini bukan sekadar alat bantu, melainkan sistem sosial dan ekonomi yang dibentuk oleh kepentingan ideologis dan komersial. Media sosial, misalnya, dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna melalui algoritma yang memprioritaskan konten emosional, provokatif, dan polaristik. Ini bukan kecelakaan, tapi ini adalah desain.
Dalam sistem semacam ini, disinformasi menyebar lebih cepat dari klarifikasi, dan ujaran kebencian lebih viral dari pesan damai. Algoritma tak hanya mengkurasi informasi, tapi juga dapat menggiring opini publik. Ia menjadi “otoritas epistemik” baru—dapat menentukan apa yang layak diketahui, dilihat, dan dipercayai. Di sinilah akar dari segala krisis digital kita: realitas dibentuk bukan oleh kebenaran, tetapi oleh keterlibatan (engagement), klik, dan impresi. Kebenaran menjadi subordinat dari performativitas.
Ironisnya, ruang digital yang dibayangkan sebagai tempat terbuka dan demokratis justru menjadi arena eksklusif yang sering memperkuat bias, memperdalam jurang sosial, dan mengikis empati. Keberadaan akun anonim, penggunaan avatar, dan sistem komunikasi tanpa tatap muka menciptakan ilusi kebebasan tanpa konsekuensi. Orang merasa bebas melontarkan hinaan, menyebar hoaks, atau mempermalukan orang lain tanpa merasa bersalah, karena kehilangan koneksi dengan sisi manusia dari lawan bicaranya.
Fenomena ini bukan sekadar masalah etika personal. Ia adalah hasil dari struktur komunikasi yang terpisah dari empati, dari sistem yang memproduksi interaksi sosial sebagai angka: views, likes, shares. Di sinilah agama perlu masuk sebagai kekuatan yang tidak hanya menyerukan etika, tetapi juga mengkritik struktur digital yang mendorong dehumanisasi. Namun sayangnya, sebagian besar institusi agama masih gagap membaca realitas seperti saat ini. Alih-alih melontarkan kritik, mereka lebih sibuk mempertahankan “kesucian simbolik” di tengah pusaran kebisingan digital.
Respons komunitas beragama terhadap transformasi digital cenderung reaktif dan defensif. Banyak tokoh agama masih terjebak dalam dikotomi lama antara “agama” dan “teknologi”, seolah-olah keduanya adalah entitas yang saling bertentangan. Teknologi dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai luhur agama, dan ruang digital dipandang sebagai ladang kebobrokan moral yang harus dihindari.
Padahal, persoalan hari ini jauh lebih kompleks. Dunia digital bukan hanya soal konten bermuatan negatif atau pornografi daring. Lebih jauh ia adalah dunia di mana identitas dipertaruhkan, kebenaran dinegosiasikan, dan eksistensi manusia dipantulkan melalui layar. Jika agama hanya hadir sebagai suara nostalgia yang membangga-banggakan masa lalu, maka ia akan tertinggal dari arus sejarah dan kehilangan relevansinya di mata generasi yang selanjutnya.
Agama seharusnya menyadari bahwa nilai-nilainya kini sedang diuji dalam sistem sosial baru. Misalnya, prinsip fastabiqul khairat (berlomba dalam kebaikan) dalam Islam, kasih dalam Kekristenan, atau ahimsa dalam Hindu dan Buddha harus diterjemahkan ke dalam perilaku digital yang konkret. Namun lebih dari itu, agama juga perlu mendorong rekonstruksi sistem digital yang adil—yang tidak sekadar mendewakan keterlibatan, tetapi menjunjung kembali integritas, keadilan informasi, dan perlindungan terhadap yang rentan.
Untuk menjawab tantangan ini, langkah pertama adalah reformasi tafsir keagamaan. Tafsir literalistik, ahistoris, dan sempit tidak akan mampu menghadapi dunia yang terus berubah. Tafsir keagamaan harus kontekstual, progresif, dan terbuka terhadap kritik. Misalnya, prinsip menjaga kehormatan sesama (hifzh al-‘ird dalam maqashid syariah) bisa menjadi landasan untuk melawan perundungan digital, doxing, dan eksploitasi data pribadi.
Langkah kedua adalah pendidikan agama yang adaptif. Pendidikan agama tidak boleh hanya berbentuk hafalan doktrin, tetapi harus mencetak peserta didik yang berpikir kritis, sadar akan teknologi, dan memiliki sensitivitas etika digital yang kuat. Kurikulum pendidikan agama seharusnya berbicara tentang hoaks, literasi media, privasi digital, dan tanggung jawab bermedia. Ini membutuhkan kolaborasi di antara para tokoh agama, akademisi, pendidik, dan pakar teknologi.
Salah satu kekeliruan umum dalam merespons tantangan digital saat ini adalah memasrahkan seluruh beban pada individu. Kita sering mendengar seruan lantang seperti “jadilah pengguna internet yang bijak”, atau “saringlah sebelum sharing”. Meskipun hal ini penting, pendekatan ini terlalu bersifat sempit dan tidak menyentuh akar persoalan yang harus dihadapi. Masalah utamanya terletak pada sistem digital yang dikendalikan oleh kepentingan kapitalisme platform—yang lebih peduli pada data dan profit dibanding kebenaran dan keadilan.
Dengan demikian, agama dalam konteks ini, harus bergerak melampaui etika individual menuju advokasi keadilan struktural. Ia harus menyuarakan perlunya regulasi algoritma yang transparan, perlindungan data pribadi, hak untuk dilupakan (right to be forgotten), dan batasan terhadap kekuasaan platform digital. Ajaran keagamaan mengenai keadilan (adl), martabat manusia (karamah), dan tanggung jawab kolektif (mas’uliyyah jamaiyah) dapat menjadi dasar perjuangan ini.
Agama hari ini dihadapkan pada pilihan historis: tetap menjadi simbol identitas yang defensif, atau tampil sebagai kekuatan reflektif yang relevan dalam menghadapi tantangan era digital.
Dalam dunia yang dikuasai oleh algoritma dan dominasi platform digital, agama tidak lagi cukup hanya berbicara dan memperdebatkan perihal etika personal atau sekadar menyerukan moralitas individual. Ia harus ikut hadir sebagai kekuatan sosial dan kultural yang mampu membongkar segala akar struktural dari krisis digital—mulai dari sistem algoritma yang diskriminatif, model bisnis yang eksploitatif, hingga budaya digital yang semakin menipiskan empati.
Untuk itu, agama harus bersifat reflektif, dengan berani mengevaluasi bagaimana cara pandang lama yang sudah tak lagi memadai. Ia harus bersikap adaptif, dengan membuka diri terhadap realitas digital dan memahami kompleksitas sosial baru yang ditimbulkannya. Dan yang tak kalah penting, agama juga harus progresif, yaitu berani melampaui sekadar penjaga tradisi menuju agen transformasi sosial yang memperjuangkan keadilan digital dan perlindungan martabat manusia dalam ruang maya.
Di tengah fragmentasi informasi, kehilangan arah moral, dan krisis identitas digital, agama dapat menjadi sumber harapan besar. Namun, harapan ini hanya bisa terwujud apabila agama tidak berhenti pada romantisme masa lalu, melainkan terlibat aktif dalam pembentukan masa depan yang lebih baik. Kita membutuhkan agama yang tidak hanya mengajarkan doa dan tata ibadah saja, tetapi juga membela hak digital, memperjuangkan keadilan informasi, dan memastikan bahwa teknologi yang melayani kemanusiaan—bukan malah sebaliknya.