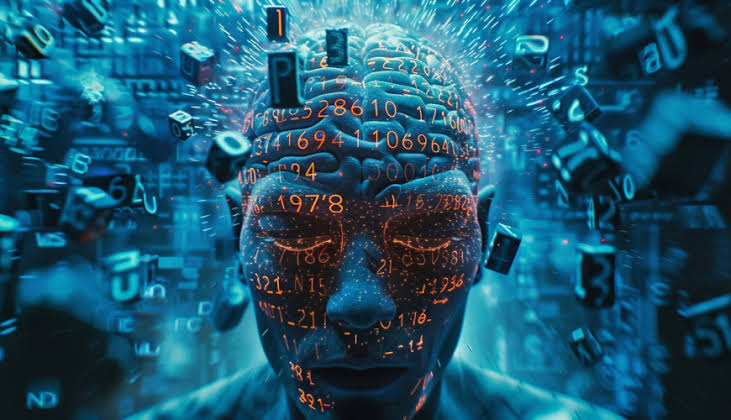Agama, dalam perjalanan sejarah peradaban manusia, selalu memainkan peran sentral dalam membentuk nilai, norma, dan struktur sosial. Ia bukan semata sistem kepercayaan terhadap realitas metafisik, tetapi juga sebagai fondasi etis yang membimbing manusia dalam menghadapi kompleksitas kehidupan.
Namun di era digital—di mana kehidupan manusia mulai tenggelam dalam algoritma, data, dan ilusi konektivitas global—agama dihadapkan pada tantangan baru: bagaimana tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman yang tidak lagi tunduk pada logika moral konvensional?

Kemajuan teknologi digital, terutama internet, kecerdasan buatan (AI), dan media sosial, telah mengubah secara radikal cara manusia berinteraksi, berpikir, bahkan memahami realitas. Transformasi ini tidak bersifat kosmetik, melainkan struktural.
Dalam konteks tersebut, pendekatan keagamaan yang bersifat moralistik dan individualistik saja menjadi tidak lagi memadai. Agama tidak cukup hanya mengingatkan umat untuk “berakhlak baik” di dunia maya; ia harus mampu memetakan persoalan sistemik yang membuat ruang digital begitu rentan terhadap kekerasan simbolik, polarisasi, dan manipulasi kebenaran.
Kita sering kali terjebak pada pandangan bahwa teknologi bersifat netral; bahwa ia hanya sebagai alat, tergantung pada siapa yang menggunakannya. Narasi ini tidak hanya naif, tetapi juga berbahaya. Sebab, teknologi digital saat ini bukan sekadar alat bantu, melainkan sistem sosial dan ekonomi yang dibentuk oleh kepentingan ideologis dan komersial. Media sosial, misalnya, dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna melalui algoritma yang memprioritaskan konten emosional, provokatif, dan polaristik. Ini bukan kecelakaan, tapi ini adalah desain.
Dalam sistem semacam ini, disinformasi menyebar lebih cepat dari klarifikasi, dan ujaran kebencian lebih viral dari pesan damai. Algoritma tak hanya mengkurasi informasi, tapi juga dapat menggiring opini publik. Ia menjadi “otoritas epistemik” baru—dapat menentukan apa yang layak diketahui, dilihat, dan dipercayai. Di sinilah akar dari segala krisis digital kita: realitas dibentuk bukan oleh kebenaran, tetapi oleh keterlibatan (engagement), klik, dan impresi. Kebenaran menjadi subordinat dari performativitas.